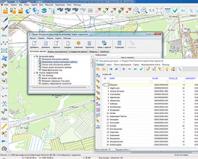Apa itu kekerasan, sebagai cita-cita dan manifestasi kejahatan. Apa hubungan antara kekerasan dan kebebasan, kekerasan dan Hukum, kekerasan dan moralitas? Hubungan antara konsep kejahatan dan kekerasan, filsafat
Dalam memahami fenomena kekerasan, terdapat dua pendekatan ekstrem, yaitu pendekatan luas (absolutis) dan pendekatan sempit (pragmatis), yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Dalam arti luas, kekerasan mengacu pada penindasan terhadap seseorang dalam segala ragam dan bentuknya - tidak hanya langsung, tetapi juga tidak langsung, tidak hanya fisik, tetapi juga ekonomi, politik, psikologis, dan lainnya. Dalam hal ini, penindasan dianggap sebagai pembatasan kondisi pengembangan pribadi, yang alasannya terletak pada orang lain atau lembaga publik. Dalam arti sempit, kekerasan biasanya mengacu pada penderitaan fisik dan ekonomi yang dilakukan orang terhadap satu sama lain, dan dipahami sebagai penganiayaan tubuh, pembunuhan, perampokan, pembakaran, dan lain-lain. Kesulitan yang terkait dengan definisi kekerasan teratasi jika kita menempatkannya dalam ruang kehendak bebas dan menganggapnya sebagai salah satu jenis hubungan kekuasaan-kehendak antar manusia.
Kekerasan adalah salah satu cara untuk memastikan dominasi, kekuasaan manusia atas manusia. Alasan yang membuat seseorang mendominasi, menguasai orang lain, menggantikannya, mengambil keputusan, bisa berbeda-beda:
a) beberapa keunggulan nyata dalam keadaan kemauan - kasus tipikal: kekuatan paternalistik, kekuatan ayah;
b) kesepakatan bersama awal - kasus tipikal: supremasi hukum dan penguasa yang sah;
c) kekerasan - kasus khas: kekuasaan penjajah, penakluk, pemerkosa.
Kekerasan bukanlah pemaksaan pada umumnya, bukan pengrusakan jiwa dan harta benda secara umum, melainkan pemaksaan dan pengrusakan yang dilakukan di luar kehendak orang atau orang yang menjadi sasaran kekerasan tersebut. Dalam konsep kekerasan, ada dua hal yang penting:
a) fakta bahwa seseorang akan menekan keinginan lain atau menundukkannya pada dirinya sendiri;
b) bahwa hal ini dilakukan melalui pengaruh yang membatasi secara eksternal, paksaan fisik.
Konsep kekerasan memiliki muatan yang cukup spesifik dan ketat, tidak dapat diidentikkan dengan segala bentuk pemaksaan. Kekerasan sebagai suatu bentuk hubungan sosial tertentu harus dibedakan, di satu sisi, dari sifat naluriah-alamiah seseorang, dan di sisi lain, dari bentuk-bentuk pemaksaan lain dalam masyarakat, khususnya yang bersifat paternalistik dan legal.
Keberadaan umat manusia membuktikan bahwa nir-kekerasan menang atas kekerasan. Meluasnya nir-kekerasan merupakan landasan penting kehidupan secara umum. Kekhasan bentuk kehidupan manusia adalah bahwa mengatasi kekerasan menjadi upaya sadar dan kegiatan yang bertujuan.
Kekerasan dan negara. Sikap negara terhadap kekerasan dicirikan oleh tiga ciri utama. Negara:
a) memonopoli kekerasan,
6) melembagakannya
c) mengganti dengan bentuk tidak langsung.
Di negara, kekerasan dilembagakan: hak atas kekerasan diformalkan dalam undang-undang. Kepatuhan setiap kasus kemungkinan penggunaan kekerasan terhadap hukum ditetapkan melalui prosedur khusus yang melibatkan penyelidikan dan pembahasan yang obyektif, seimbang, dan komprehensif. Kekerasan yang dilakukan negara didasarkan pada nalar dan bercirikan ketidakberpihakan.
Negara telah membuat kemajuan signifikan dalam membatasi kekerasan. Hal ini melengkapi perjuangan langsung melawan kekerasan dengan memberikan dampak proaktif terhadap keadaan yang dapat memicu terjadinya kekerasan. Di negara bagian ini, kekerasan sebagian besar digantikan oleh ancaman kekerasan.
Betapapun sah, terlembaganya, dan bersifat pencegahannya kekerasan negara, tetap saja kekerasan – dan dalam pengertian ini, kekerasan tersebut bertentangan dengan moralitas. Monopoli atas kekerasan menyebabkan terjadinya kekerasan yang berlebihan. Institusionalitas kekerasan memberikan anonimitas dan menumpulkan persepsinya. Sifat kekerasan yang tidak langsung (manipulasi kesadaran, eksploitasi tersembunyi, dll.) memperluas cakupan penerapannya.
Sikap terhadap kekerasan negara bisa sangat berbeda jika kita menganggapnya sebagai bentuk pembatasan kekerasan, sebuah tahapan dalam upaya mengatasi kekerasan. Pelembagaan kekerasan memasukkannya ke dalam ruang tindakan, yang legitimasinya disertai dengan pembenaran yang masuk akal dan memerlukan pembenaran tersebut; Tanpa hal ini, pertanyaan tentang diperbolehkannya kekerasan tidak akan mungkin terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan yang tersembunyi dan tidak langsung merupakan bukti bahwa keefektifannya dapat digantikan dengan cara-cara lain.
Kekerasan negara bukan sekadar pembatasan kekerasan, namun pembatasan kekerasan yang menciptakan prasyarat bagi penyelesaian akhir dan transisi menuju tatanan sosial yang pada dasarnya tanpa kekerasan.
Non-kekerasan Dalam sejarah masyarakat, non-kekerasan diekspresikan dalam bentuk non-perlawanan, meski seringkali hanya dianggap sebagai perwujudan kerendahan hati, kepasifan, dan kelemahan. Atas dasar ini, dikemukakan argumen yang mendukung kekerasan, yaitu bahwa tanpa kekerasan tidak mungkin melawan bentuk-bentuk kejahatan yang agresif (misalnya tirani). Dan betapa pun buruknya kekerasan, itu tetap lebih baik daripada ketundukan dan kepengecutan. Kekerasan dianggap dibenarkan sebagai kontra-kekerasan.
Namun argumen ini tidak sepenuhnya valid, karena ada jenis perilaku lain - perlawanan aktif tanpa kekerasan, mengatasi situasi ketidakadilan dengan menggunakan metode non-kekerasan. Perilaku seperti ini dapat dibenarkan secara moral.
Prinsip-prinsip perilaku tanpa kekerasan:
a) penolakan terhadap monopoli atas kebenaran, kesiapan untuk perubahan, dialog dan kompromi;
b) kritik terhadap perilaku sendiri untuk mengidentifikasi apa yang dapat memberi makan dan memprovokasi posisi bermusuhan lawan;
c) analisis situasi melalui sudut pandang lawan untuk memahaminya dan menemukan jalan keluar yang memungkinkan dia menyelamatkan mukanya dan keluar dari konflik dengan terhormat;
d) berperang melawan kejahatan, tetapi mencintai orang-orang di baliknya;
e) keterbukaan penuh dalam perilaku, tidak adanya kebohongan, niat tersembunyi, trik taktis, dll dalam kaitannya dengan lawan.
Pada abad kedua puluh, nir-kekerasan menjadi strategi dan teknik perjuangan sosial-politik, metode penyelesaian konflik, dan taktik mediasi. Semua ini merupakan bukti bahwa sebuah era baru sedang terbuka ketika keadilan sosial dikaitkan secara eksklusif dengan metode penyelesaian konflik kemanusiaan tanpa kekerasan.
TOPIK 2. BAIK DAN JAHAT. KEKERASAN DAN NON-KERAS
Kategori baik dan jahat, bersama dengan kewajiban, merupakan hal mendasar dalam etika. Semua teori etika dibagi menjadi aksiologis (teleologis) dan deontologis.
Teori aksiologis dibangun atas dasar pemahaman tentang kebaikan atau manfaat sebagai kategori awal yang menentukan nilai tertinggi(Aristoteles, L. Feuerbach, J. Moore). Karena mengejar kebaikan adalah tujuan akhir aktivitas, teori-teori ini disebut juga teleologis. Mereka, pada gilirannya, dapat dibagi menjadi aksiologis-ontologis dan aksiologis-psikologis. Pertama, kebaikan tampaknya datang dari suatu realitas di luar individu itu sendiri (Aristoteles), dan kedua, kebaikan itu terkandung dalam keadaan subjek itu sendiri (Democritus). Namun dalam kedua kasus tersebut, tugas hanya menunjukkan jalan menuju kebaikan atau kebahagiaan.
Teori deontologis, sebaliknya, berangkat dari keutamaan tugas (I. Kant, Ross, Rawls). Dalam teori-teori ini, kebaikan sebenarnya diidentikkan dengan kewajiban. Sebagai kategori kesadaran moral, kebaikan memperoleh makna paling penting bagi teori etika teleologis. Ini dapat didefinisikan sebagai kesesuaian perilaku dengan suatu cita-cita. Dalam arti luas, kebaikan identik dengan kebaikan. Sebenarnya inilah makna awal penggunaan konsep kebaikan. Kebaikan adalah segala sesuatu yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup, meningkatkan kekuatan keluarga, yang dapat memberikan perlindungan yang dapat diandalkan dari musuh. Oleh karena itu, kejahatan adalah kebalikannya. Lambat laun, pemahaman yang lebih sempit tentang kebaikan sebagai perilaku yang benar dirumuskan dalam ajaran etika. Artinya, fenomena seperti panen yang melimpah, hujan yang memberi kehidupan, dan lain-lain sudah tidak dianggap baik lagi. Setelah itu, kategori baik dan baik mendapat definisi yang berbeda. Kebaikan ternyata lebih luas dibandingkan kebaikan moral. Kategori kejahatan terus digunakan sebagai lawan kata baik dan baik.
Konsep baik dan jahat berikut ini dikenal dalam filsafat.
1. Intelektualisme etis, atau konsep pencerahan, yang menyatakan bahwa kejahatan dikaitkan dengan ketidaktahuan. Cukup dengan memperbaiki sistem pendidikan, dan kejahatan akan hilang, Socrates percaya, dan para Pencerah berpikir demikian. Perlu dikembangkan kecerdasan, pendidikan, dan peningkatan ilmu pengetahuan.
2. Optimisme etis, yang berpendapat bahwa kejahatan adalah bagian kecil dari dunia di mana segala sesuatu cenderung menuju kebaikan (Stoa). Kejahatan bahkan diperlukan untuk membangun kebaikan. Segala sesuatu yang bagi kita tampak jahat sebenarnya melayani ketertiban dan keindahan dunia secara keseluruhan. Dunia secara keseluruhan baik. Dalam kerangka pendekatan ini, kejahatan biasanya dipandang sebagai ujian sementara yang pada akhirnya memenuhi tujuan kemenangan keadilan dan kebenaran (Plotinus, G. Leibniz).
3. Determinisme sosial melihat sumber kejahatan terletak pada ketidaksempurnaan dan ketidakadilan sosial (Marxisme). Penyebab kejahatan bukanlah pada lemahnya akal, tetapi pada kondisi sosial yang buruk: kemiskinan, pendidikan yang buruk, kondisi kehidupan yang sulit - semua ini menjadi dasar untuk melakukan tindakan keji.
4. Teori-teori psikoanalisis melihat sumber kejahatan pada sifat manusia, yaitu pada alam bawah sadar (A. Schopenhauer, Z. Freud, F. Nietzsche, E. Fromm).
5. Teori antropologi (M. Buber, M. Scheler, E. Fromm) melanjutkan garis psikoanalisis, menganggap kejahatan sebagai karakteristik yang lebih mendasar dan utama dari seseorang, mendefinisikan esensinya yang terdalam namun tersembunyi dengan cermat. Baik dan jahat dalam realitas antropologisnya bukanlah dua struktur yang homogen, seperti yang biasa dianggap, melainkan sepenuhnya heterogen. Mereka tidak dirasakan oleh seseorang pada saat yang bersamaan. Konsep kebaikan bersifat sekunder, sedangkan kejahatan bersifat primordial dan primer.
6. Filsafat moral Rusia mengidentifikasi kebaikan dan peningkatan moral pribadi seseorang, peningkatan spiritualitas dan humanisasi seluruh masyarakat.
Baik dan buruk- konsep kesadaran moral yang paling umum, membedakan antara moral dan tidak bermoral. Ini adalah karakteristik etis universal dari semua aktivitas dan hubungan manusia. Kebaikan adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan, melestarikan, dan memperkuat kebaikan. Kejahatan adalah kehancuran, kehancuran kebaikan.
Berdasarkan kenyataan bahwa etika humanistik menempatkan manusia sebagai pusat, keunikan dan orisinalitasnya, kebahagiaan, kebutuhan dan kepentingannya, maka kriteria kebaikan yang pertama adalah segala sesuatu yang berkontribusi pada realisasi diri akan esensi manusia, pengungkapan dirinya, identifikasi diri. Kriteria kebaikan yang kedua dan sekaligus kondisi yang menjamin realisasi diri seseorang adalah humanisme dan segala sesuatu yang berkaitan dengan humanisasi hubungan antarmanusia. Jadi, Kebaikan dan Kejahatan memiliki isi yang berlawanan: kategori kebaikan mewujudkan gagasan orang tentang hal yang paling positif dalam bidang moralitas, tentang apa yang sesuai dengan cita-cita moral; dan dalam konsep kejahatan - gagasan yang bertentangan dengan cita-cita moral dan menghalangi tercapainya kebahagiaan dan kemanusiaan dalam hubungan antar manusia.
Fitur dan paradoks kebaikan dan kejahatan
1. Sifat universal yang umum: baik hubungan manusia maupun sikap manusia terhadap alam dan dunia berada di bawah “yurisdiksi” mereka.
2. Konkrit dan spontanitas: baik dan jahat adalah konsep sejarah yang bergantung pada hubungan sosial yang nyata dan spesifik.
3. Subjektivitas:
. mereka tidak termasuk dalam dunia objektif, tetapi bertindak dalam bidang kesadaran dan hubungan manusia, karena kebaikan dan kejahatan bukan hanya konsep berbasis nilai, tetapi juga konsep evaluatif;
. subjek yang berbeda, karena perbedaan pemahaman, minat, hubungan, mungkin memiliki gagasan berbeda tentang yang baik dan yang jahat;
. apa yang secara obyektif tampak baik bagi seseorang, adalah (atau tampak baginya) jahat bagi orang lain;
4. Relativitas:
. tidak adanya kebaikan dan kejahatan mutlak di dunia nyata (hanya mungkin terjadi dalam abstraksi atau di dunia lain);
. kejahatan dalam kondisi dan hubungan tertentu dapat tampak baik dalam kondisi dan hubungan lain;
. dalam proses perkembangan, apa yang tadinya jahat bisa berubah menjadi baik dan sebaliknya.
5. Kesatuan dan hubungan yang tidak dapat dipisahkan: kebaikan dan kejahatan tidak ada sebagai fenomena yang terpisah. Pada kenyataannya, ada hal-hal nyata yang menurut prinsip “yang” dan “yin”, terkandung kebaikan dan kejahatan. Terlebih lagi, karena relativitasnya, kebaikan mengandung unsur kejahatan; kejahatan mengandaikan kehadiran kebaikan.
6. Kesatuan antara yang baik dan yang jahat adalah kesatuan yang saling bertentangan: keduanya tidak hanya saling meniadakan, tetapi juga saling meniadakan.
7. Saling mengecualikan menentukan perjuangan terus-menerus antara yang baik dan yang jahat, yang dengan demikian menjadi cara keberadaan mereka, karena perjuangan ini tidak dapat berakhir dengan kemenangan akhir kedua belah pihak.
Masalah pergulatan antara yang baik dan yang jahat
Kebaikan dan kejahatan yang tidak terkalahkan tidak berarti bahwa perjuangan mereka tidak ada artinya dan tidak perlu. Makna dari perjuangan ini adalah untuk mengurangi “jumlah” kejahatan dengan segala cara dan meningkatkan “jumlah” kebaikan di dunia, dan pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara dan cara untuk mencapai hal ini.
Perdebatan utama adalah antara pendukung perang melawan kejahatan dari posisi yang kuat dan pendukung etika non-kekerasan, berdasarkan gagasan non-perlawanan terhadap kejahatan melalui kekerasan. Di sini, nir-kekerasan dipandang sebagai cara yang paling efektif dan memadai untuk melawan kejahatan, sebagai satu-satunya jalan nyata menuju keadilan, karena semua jalan lain terbukti tidak efektif.
Kekerasan dan non-kekerasan merupakan pasangan dialektis seperti kiri dan kanan, atau mewakili tahapan berbeda dalam perkembangan proses yang sama. Pertanyaannya adalah apakah konsep-konsep ini mengungkapkan cara-cara bertindak yang alternatif atau yang terus berubah.
1. Ada dua pendekatan untuk memahami kekerasan, yang satu bisa disebut absolut, yang lain pragmatis. Menurut yang pertama, konsep kekerasan membawa muatan evaluatif negatif yang jelas dan digunakan dalam arti yang sangat luas, termasuk segala bentuk penindasan fisik, psikologis, ekonomi dan kualitas mental yang terkait, seperti kebohongan, kebencian, kemunafikan, dll. Ia secara langsung diidentifikasikan (dalam semua manifestasinya yang beragam) dengan kejahatan pada umumnya. Pendekatan pragmatis berfokus pada definisi kekerasan yang netral nilai dan obyektif serta mengidentifikasikannya dengan kerusakan fisik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh manusia terhadap satu sama lain. Penafsiran ini memungkinkan kita untuk mengajukan pertanyaan tentang pembenaran kekerasan, kemungkinan penggunaannya dalam situasi tertentu, namun tidak ada kriteria untuk penyelesaiannya.
2. Non-kekerasan, tidak seperti kekerasan, bukanlah kasus khusus dari keterhubungan hierarkis dari keinginan manusia, namun prospek perpaduan solidaritasnya. Non-kekerasan berasal dari keyakinan akan nilai hakiki setiap orang sebagai makhluk bebas dan sekaligus keterhubungan timbal balik semua orang dalam kebaikan dan kejahatan. Perlu dicatat bahwa salah satu keberatan yang sering diulang-ulang terhadap non-kekerasan sebagai sebuah program sejarah adalah bahwa non-kekerasan berasal dari konsepsi manusia yang terlalu ramah dan karena itu realistis. Kenyataannya tidak demikian. Menganggap seseorang sangat jahat berarti memfitnahnya secara tidak adil. Menganggap seseorang sangat baik berarti menyanjungnya secara terbuka. Haknya diberikan ketika ambivalensi moral seseorang diketahui. Dengan demikian, konsep kekerasan dan non-kekerasan tidak dapat dipahami tanpa korelasi satu sama lain. Untuk mengungkap sifat spesifik dari korelasi ini, hal-hal tersebut tidak harus dilihat secara terpisah, namun dalam konteks yang lebih luas yaitu perjuangan kebaikan melawan kejahatan, perjuangan untuk keadilan sosial dan solidaritas manusia.
Kekerasan dan non-kekerasan mewakili perspektif yang berbeda dalam perjuangan untuk hubungan yang adil antar manusia dalam masyarakat. Bahaya global yang mengancam umat manusia – nuklir, lingkungan hidup, demografi, antropologi dan lain-lain – telah menghadapkan kita pada pertanyaan yang fatal: apakah kita akan meninggalkan kekerasan, “etika permusuhan”, atau kita akan binasa sama sekali. Filsafat dan etika nir-kekerasan saat ini bukan lagi sekedar tindakan kekudusan individu, namun telah memperoleh makna sejarah yang sangat relevan.
Prinsip dasar etika non-kekerasan. Pertama, dengan membalas kejahatan dengan kekerasan, kita tidak mengalahkan kejahatan, karena kita tidak meneguhkan kebaikan, namun sebaliknya, kita menambah jumlah kejahatan di dunia. Kedua, non-kekerasan mematahkan “logika kebalikan” kekerasan, yang menimbulkan efek “bumerang kejahatan” (L. Tolstoy), yang menurutnya kejahatan yang telah Anda lakukan pasti akan kembali kepada Anda. Ketiga, tuntutan nir-kekerasan mengarah pada kemenangan kebaikan, karena hal itu berkontribusi pada kemajuan manusia. Keempat, tanpa menanggapi kejahatan dengan kekerasan, kita melawan kejahatan bukan dengan ketidakberdayaan, namun dengan kekuatan, karena “memberi pipi” lebih sulit daripada sekadar “memberi kembali”. Dengan demikian, non-kekerasan bukanlah dorongan terhadap kejahatan atau kepengecutan, tetapi kemampuan untuk melawan kejahatan dan melawannya tanpa kehilangan diri sendiri dan tanpa jatuh ke tingkat kejahatan.
Para pendukung bentuk perjuangan kekerasan melawan kejahatan, meski tidak menganggap kekerasan sebagai fenomena positif, namun mengajukan argumen mereka sendiri. Pertama, mereka menganggap kekerasan lebih sebagai suatu kebutuhan yang dipaksakan dibandingkan sebagai suatu keadaan yang diinginkan. Argumen utama mereka dalam membela kekerasan adalah impunitas kejahatan dalam kondisi non-kekerasan. Kedua, para penentangnya melihat kurangnya etika non-kekerasan dalam gagasannya yang terlalu ideal tentang seseorang. Faktanya, konsep perjuangan tanpa kekerasan didasarkan pada pengakuan akan dualitas moral sifat manusia - kesatuan prinsip baik dan jahat. Hal ini mengandaikan adanya strategi dan taktik tertentu dalam memerangi kejahatan, yang tujuannya adalah untuk memperkuat dan meningkatkan kebaikan. Jika kekerasan ditujukan untuk menekan atau menghancurkan musuh dan hanya untuk sementara meredam konflik, maka strategi dan taktik perjuangan non-kekerasan ditujukan untuk menghilangkan akar penyebab konflik. Oleh karena itu, para pendukung nir-kekerasan mengambil tanggung jawab atas kejahatan yang mereka lawan dan memperkenalkan “musuh” kepada kebaikan yang atas nama perjuangan tersebut dilakukan.
A.A.GUSEINOV
Saya ingin membatasi topik laporan ini pada pertanyaan tentang hubungan antara konsep kekerasan dan non-kekerasan. Lebih khusus lagi, analisis apakah konsep-konsep tersebut merupakan pasangan dialektis seperti kiri dan kanan atau mewakili tahapan berbeda dalam perkembangan proses yang sama. Pertanyaannya adalah apakah konsep-konsep ini mengungkapkan cara-cara bertindak yang alternatif atau yang terus berubah.
1. Dalam mendefinisikan konsep kekerasan, ada dua pendekatan, yang satu bisa disebut absolutis, yang lain pragmatis.
Menurut yang pertama, konsep kekerasan membawa muatan evaluatif negatif yang jelas, namun kata ini sudah ada dalam bahasa alami; Terlebih lagi, kekerasan digunakan dalam arti yang sangat luas, termasuk segala bentuk penindasan fisik, psikologis, ekonomi dan kualitas mental yang terkait, seperti kebohongan, kebencian, kemunafikan, dll. Kekerasan, pada kenyataannya, diidentifikasi secara langsung (dalam segala hal). beragam manifestasi) dengan kejahatan pada umumnya. Dengan pendekatan ini, setidaknya ada dua kesulitan yang muncul: pertama, masalah pembenaran kekerasan dan kemungkinan penggunaan konstruktifnya dihilangkan; konsep itu sendiri seolah-olah menentukan suatu masalah, sejak awal memuat jawaban atas pertanyaan yang sedang dibahas. Kedua, penolakan terhadap kekerasan tampak seperti program moral murni yang berkonfrontasi dengan kehidupan nyata. Bukan suatu kebetulan bahwa, misalnya, L.N. Tolstoy, yang paling konsisten menganut tradisi intelektual dan spiritual ini, dengan memberikan makna yang murni negatif dan sangat luas ke dalam konsep kekerasan, pada saat yang sama adalah seorang kritikus radikal terhadap peradaban modern, semuanya bentuk-bentuk egoisme dan paksaan yang melekat; baginya, khususnya, dalam hal sikap terhadap kekerasan, tidak ada banyak perbedaan antara perampok dan raja yang sah, dan jika ada, hal itu tidak menguntungkan raja yang sah. Moralisasi absolutisme, menurut pendapat saya, adalah salah satu alasan utama mengapa ide-ide non-kekerasan saat ini, di akhir abad ke-20, mendapat tanggapan yang hampir sama di masyarakat dibandingkan dua setengah ribu tahun yang lalu, ketika ide-ide tersebut pertama kali muncul. . Manusia bukanlah malaikat; Anda boleh menyesalinya, tetapi Anda tidak bisa mengubah keadaan ini.
Pendekatan pragmatis berfokus pada definisi kekerasan yang netral nilai dan obyektif serta mengidentifikasikannya dengan kerugian fisik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh orang terhadap satu sama lain; kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang jelas-jelas merupakan kekerasan - pembunuhan, perampokan, dll. Penafsiran ini memungkinkan kita untuk mengajukan pertanyaan tentang pembenaran kekerasan, kemungkinan penggunaannya dalam situasi tertentu, tetapi tidak ada kriteria untuk penyelesaiannya.
Argumen yang umum adalah bahwa kekerasan dibenarkan dalam dosis yang relatif kecil - dalam kasus di mana kekerasan dapat mencegah kekerasan yang lebih besar, yang, terlebih lagi, tidak dapat dicegah dengan cara lain apa pun. Terkait hal ini, pertama-tama perlu dicatat bahwa tidak ada satuan untuk mengukur kekerasan. Masalahnya menjadi tidak ada harapan lagi ketika menyangkut pencegahan kekerasan. Tolstoy berkata: sebelum kekerasan terjadi, seseorang tidak akan pernah bisa mengatakan dengan pasti bahwa kekerasan akan terjadi, dan oleh karena itu upaya untuk membenarkan suatu kekerasan dengan alasan untuk mencegah kekerasan lainnya akan selalu rentan secara logika dan dipertanyakan secara moral. Kekerasan tidak dapat dihitung atau diukur, meskipun kekerasan tersebut dapat ditangkap secara eksternal. Faktanya, kekerasan tidak hanya terbatas pada manifestasi eksternal saja. Rasa sakit akibat dislokasi bahu yang tidak disengaja dan rasa sakit akibat pukulan tongkat polisi anti huru hara adalah rasa sakit yang berbeda, dan seseorang mungkin lebih memilih rasa sakit yang pertama daripada yang kedua, meskipun secara kuantitatif seribu kali lebih besar. Tidak mungkin untuk menunjukkan perbedaan ini sambil tetap berada dalam batas-batas definisi obyektivis yang ketat. Masalah sikap terhadap kekerasan dengan demikian kehilangan ketegangan moralnya.
Kesulitan yang terkait dengan definisi kekerasan teratasi jika kita menempatkannya dalam ruang kehendak bebas dan menganggapnya sebagai salah satu jenis hubungan kekuasaan-kehendak antar manusia. Kant, dalam Critique of Judgment (§ 28), mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemampuan untuk mengatasi rintangan besar. Kekuatan yang sama disebut kekuatan (Gewalt) jika ia dapat mengatasi perlawanan dari kekuatan itu sendiri.” Dengan kata lain, kekuasaan dalam hubungan antarmanusia dapat didefinisikan sebagai pengambilan keputusan bagi orang lain, melipatgandakan, memperkuat keinginan seseorang dengan mengorbankan keinginan orang lain. Kekerasan adalah salah satu cara untuk memastikan dominasi, kekuasaan manusia atas manusia. Alasan mengapa seseorang mendominasi, menguasai yang lain, menggantikannya, mengambil keputusan, bisa berbeda: a) beberapa keunggulan nyata dalam keadaan kemauan: kasus yang khas adalah kekuasaan paternalistik, kekuasaan ayah; b) kesepakatan awal bersama: kasus tipikal adalah supremasi hukum dan penguasa yang sah; c) kekerasan: kasus yang khas adalah kekuasaan penjajah, penakluk, pemerkosa. Jadi, kekerasan bukanlah pemaksaan pada umumnya, bukan perusakan jiwa dan harta benda pada umumnya, melainkan pemaksaan dan pengrusakan yang dilakukan di luar kehendak orang atau orang yang menjadi sasarannya. Kekerasan adalah perampasan kehendak bebas. Ini merupakan serangan terhadap kebebasan berkehendak manusia.
Dengan pemahaman tersebut, konsep kekerasan memperoleh makna yang lebih spesifik dan ketat dibandingkan jika hanya diidentikkan dengan kekuasaan atau dimaknai sebagai kekuatan destruktif yang umum. Hal ini memungkinkan kekerasan sebagai bentuk hubungan sosial tertentu untuk dibedakan, di satu sisi, dari sifat alami naluriah seseorang: agresivitas, permusuhan, karnivora, dan di sisi lain, dari bentuk pemaksaan lain dalam masyarakat, khususnya. , paternalistik dan legal. Pada saat yang sama, jebakan aksiologis yang melekat dalam absolutisme etis telah diatasi dan pertanyaan tentang pembenaran kekerasan tetap terbuka untuk diskusi yang masuk akal.
Persoalan pembenaran atas kekerasan tidak terkait dengan kehendak bebas secara umum, namun dengan kepastian moralnya, dengan karakteristik substantif spesifiknya sebagai kehendak baik atau jahat. Ketika berbicara tentang pembenaran atas kekerasan, mereka biasanya hanya mempertimbangkan satu aspek - kepada siapa kekerasan itu ditujukan. Namun pihak lain juga tidak kalah pentingnya – siapa yang dapat, jika memiliki alasan yang cukup, melakukan kekerasan jika kita menyadari bahwa dalam beberapa kasus hal tersebut sepenuhnya dapat dibenarkan. Lagi pula, memutuskan siapa yang bisa menjadi korban saja tidak cukup. Kami masih harus menjawab siapa yang pantas menjadi hakim. Secara umum, perlu dicatat bahwa argumen yang paling kuat dan sejauh ini tidak terbantahkan menentang kekerasan terdapat dalam kisah Injil tentang seorang perempuan yang dirajam. Siapa, orang suci apa, yang dapat menyebut kita sebagai penjahat yang harus dimusnahkan? Dan jika seseorang mengambil hak untuk menghakimi, lalu apa yang menghalangi orang lain untuk menyatakan dirinya sebagai penjahat? Bagaimanapun, seluruh masalah muncul karena fakta bahwa orang tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pertanyaan tentang apa yang dianggap jahat dan apa yang baik, mereka tidak dapat mengembangkan kriteria kejahatan yang diakui secara universal dan tanpa syarat. Dan dalam situasi ini tidak ada jalan keluar lain yang positif dan menyelamatkan nyawa kecuali mengakui kehidupan manusia itu sendiri sebagai nilai absolut dan sepenuhnya meninggalkan kekerasan. Pada suatu waktu, Ernst Haeckel, berdasarkan hukum alam perjuangan untuk eksistensi, mencoba membenarkan keadilan dan manfaat hukuman mati, sebagaimana ia katakan, “penjahat dan bajingan yang tidak dapat diperbaiki.” Menolaknya, LN Tolstoy bertanya: “Jika membunuh orang jahat itu berguna, lalu siapa yang akan memutuskan siapa yang jahat? Misalnya, saya percaya bahwa saya tidak mengenal siapa pun yang lebih buruk dan lebih berbahaya daripada Tuan Haeckel; haruskah saya dan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama menghukum gantung Tuan Haeckel?”
Dalam kerangka definisi yang saya usulkan, niat yang benar-benar baik bisa saja mempunyai hak untuk menggunakan kekerasan, dan pembenaran penggunaannya bisa jadi karena niat tersebut ditujukan terhadap niat yang benar-benar jahat. Akan tetapi, kehendak manusia tidak bisa bersifat mutlak (seluruhnya) baik atau mutlak (seluruhnya) jahat. Keduanya merupakan kontradiksi dalam definisi. Niat yang benar-benar baik tidak mungkin terjadi karena paradoks kesempurnaan moral. Kehendak yang benar-benar jahat tidak mungkin terjadi, karena keinginan seperti itu akan menghancurkan dirinya sendiri.
2. Non-kekerasan, tidak seperti kekerasan, bukanlah kasus khusus dari keterhubungan hierarkis dari keinginan manusia, namun prospek perpaduan solidaritasnya. Koordinatnya bukanlah hubungan kekuasaan vertikal, melainkan komunikasi persahabatan secara horizontal, sedangkan pengertian persahabatan dalam pengertian Aristoteles yang luas. Non-kekerasan berasal dari keyakinan akan nilai hakiki setiap orang sebagai makhluk bebas dan sekaligus keterhubungan timbal balik semua orang dalam kebaikan dan kejahatan. Salah satu keberatan yang sering diulang-ulang terhadap non-kekerasan sebagai sebuah program sejarah adalah bahwa non-kekerasan berasal dari konsepsi manusia yang terlalu ramah dan karena itu realistis. Kenyataannya tidak demikian. Inti dari nir-kekerasan adalah konsep bahwa jiwa manusia adalah arena pertarungan antara yang baik dan yang jahat, seperti yang ditulis oleh Martin Luther King, “bahkan dalam diri kita yang terburuk pun terdapat kebaikan, dan dalam diri kita yang terbaik terdapat kebaikan. adalah bagian dari kejahatan.” Menganggap seseorang sangat jahat berarti memfitnahnya secara tidak adil. Menganggap seseorang sangat baik berarti menyanjungnya secara terbuka. Haknya diberikan ketika ambivalensi moral seseorang diketahui.
Setidaknya ada dua kesimpulan etis penting yang mengikuti postulat kebebasan manusia. Yang pertama adalah seseorang terbuka terhadap kebaikan dan kejahatan. Klaim bahwa bukti terbaik keberadaan kehendak bebas adalah bahwa tanpa kehendak bebas, mustahil seseorang berbuat dosa, lebih dari sekadar proposisi yang cerdas. Itu hanya cerdas. Kedua, tidak mungkin menjawab pertanyaan tentang apa itu seseorang tanpa sekaligus menjawab pertanyaan tentang apa yang harus ia lakukan. Kebaikan, seperti halnya kejahatan, bukanlah fakta. Ini adalah masalah pilihan. Manusia bukanlah binatang. Dan manusia bukanlah Tuhan. Dia adalah persilangan antara keduanya. Seseorang tidak identik dengan dirinya sendiri. Manusia adalah seorang musafir. Yang penting bukan di mana dia berada. Yang penting adalah kemana dia akan pergi dan kemauannya untuk pergi dan mencapai tujuan.
“Pertanyaan tentang jaman sekarang ini dapat dijawab dengan jelas - di era kekerasan super. Ia melayang di mana-mana di dunia modern, menembus ke dalam semua pori-pori masyarakat: politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya." Pernyataan filsuf Amerika L. Tiger yang terkesan apokaliptik ini mencerminkan situasi konflik umum saat ini dan lonjakan konflik dalam segala bentuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. kekerasan dan manifestasi agresivitas dan terorisme.
Sejarah, tentu saja, selalu menyeret “kereta kemenangannya” melintasi tumpukan mayat dan lautan darah. Namun drama periode saat ini terletak pada kenyataan bahwa umat manusia kini hidup dalam kondisi konfrontasi nuklir, ketika jumlah negara yang memiliki senjata dengan kekuatan destruktif yang belum pernah terjadi sebelumnya semakin meningkat. Untuk pertama kalinya, keabadian umat manusia dipertanyakan. Pertanyaan Hamlet - menjadi atau tidak? - sekarang muncul bukan dalam arti filosofis, tetapi dalam arti penting dan praktis.
Adanya jenis-jenis kekerasan yang sangat berbeda dari segi isi, fungsi dan tujuannya membuat sulit untuk menemukan ciri-ciri umum dan mengembangkan satu konsep yang diterima secara umum. Tapi kita bisa sepakat bahwa “kekerasan adalah manifestasi dari struktur keberadaan.” Ini mewakili suatu bentuk hubungan tertentu, yang pelaksanaannya dikaitkan dengan “penggunaan kekuatan”, “menyebabkan kerugian fisik, spiritual dan harta benda”, “pelanggaran kepentingan dan hak seseorang”, “penindasan kehendak bebas”. Kekerasan atau ancaman penggunaannya memaksa orang untuk berperilaku tidak sesuai dengan keinginan mereka dan menghalangi “realisasi potensi somatik dan spiritual manusia.” Definisi serupa diberikan oleh banyak peneliti tentang fenomena ini.
Dalam kekerasan sosial sebagai salah satu jenis komunikasi antarmanusia, benturan dan konfrontasi kepentingan dan tujuan subyek hubungan sosial - negara, kelas, kelompok etnis - menemukan ekspresi yang ekstrim. Manifestasi kekerasan yang paling umum meliputi perang, revolusi bersenjata, represi politik, terorisme, dan genosida.
Kekerasan berperan sebagai “bidan”, yang jasanya digunakan untuk menyelesaikan antagonisme kelas dan etnis, merevolusi penggantian rezim yang sudah ketinggalan zaman, dan membangun rezim politik dan struktur ekonomi baru. Munculnya metode-metode produksi baru terjadi di bawah pengaruh tidak hanya hukum ekonomi yang obyektif, tetapi juga memerlukan penggunaan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. K. Marx mencatat bahwa proses akumulasi kapitalis tidak dapat berjalan tanpa pengambilalihan dengan kekerasan, “transformasi masyarakat feodal pertanian menjadi masyarakat industri... dicapai tidak hanya dengan apa yang disebut cara alami, tetapi dengan bantuan cara-cara koersif. ”
Karena peran dan signifikansinya, kekerasan selalu menjadi pusat pemikiran dan praktik sosial umat manusia. Hal ini dikutuk dan dikutuk, mereka ditakuti dan diancam, hal ini dinyatakan sebagai kejahatan mutlak dan “pekerjaan Setan”, hal ini dinyatakan sebagai faktor pendorong kemajuan sosial, hal ini diagungkan dan diangkat ke dalam aliran sesat. Mungkin sulit untuk menemukan kategori khusus lain yang di dalamnya terdapat begitu banyak penilaian yang kontradiktif, yang dalam penilaiannya akan terdapat perbedaan pendapat yang tidak dapat didamaikan.
Pentingnya masalah kekerasan sosial dibuktikan dengan fakta bahwa tidak ada satupun pemikir besar di abad-abad yang lalu atau zaman modern yang mengabaikannya. Mulai dari filsafat kuno hingga saat ini, perwakilan dari berbagai aliran ideologi dan tradisi filsafat telah mempelajari sifat dan akar kekerasan serta perannya dalam sejarah. Ketertarikan yang berkelanjutan terhadap masalah ini dijelaskan oleh fakta bahwa masalah ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga bersifat politis dan memiliki signifikansi praktis saat ini. Manifestasi kekerasan berkaitan erat dengan hubungan kelas dan nasional, politik internasional, secara langsung mempengaruhi kepentingan seluruh masyarakat, dan mempengaruhi nasib seluruh umat manusia. Hal ini mengakibatkan perpecahan yang tajam dan posisi tanpa kompromi dalam isu ini di antara berbagai kelompok sosial dan kekuatan politik, yang mencerminkan kepentingan dan tujuan mereka.
Pada setiap tahapan perkembangan peradaban, masalah kekerasan mempunyai ciri khas dan ciri khas tersendiri. Perubahan kondisi sejarah juga memerlukan perubahan dalam bentuk dan metode tindakan kekerasan, korelasinya, skala dan konsekuensinya. Interpretasi konseptual terhadap fenomena ini, penilaian dan persepsinya juga perlu disesuaikan dengan realitas transformasi kehidupan dan keberadaan yang ada.
Faktor utama yang saat ini menentukan fenomena dan tren baru dalam hal ini antara lain perubahan global yang terkait dengan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergeseran geopolitik; meningkatnya kesenjangan dan konfrontasi antara negara-negara kaya yang berkembang secara dinamis dan negara-negara terbelakang yang semakin miskin, yang juga mewakili komunitas sosio-kultural yang berbeda; pertumbuhan sehubungan dengan manifestasi ekstremisme dan fundamentalisme ini. Ketegangan dan konflik internasional meningkat akibat transformasi dunia dari bipolar ke multipolar, yang menyebabkan terganggunya keseimbangan kekuatan yang ada, memperkuat ambisi imperial Amerika Serikat dan keinginannya untuk mendominasi monopoli. Kemanusiaan telah beralih dari Perang Dingin ke dunia yang sama dinginnya.
Jumlah konflik bersenjata semakin meningkat. Menurut PBB, selama dekade terakhir telah terjadi lebih dari 100 perang lokal di berbagai belahan dunia, yang melibatkan 57 negara. Telah terjadi babak baru perlombaan senjata, modernisasi kualitatif untuk meningkatkan kekuatan destruktifnya. India dan Pakistan telah mempunyai senjata nuklir, namun tampaknya sejumlah negara lain juga memilikinya, meskipun mereka tidak secara resmi tergabung dalam “klub nuklir”. Dua perang dunia di abad ke-20, tulis Erich Remarque, mungkin belum cukup menjadi pembelajaran bagi umat manusia. “Dunia sekali lagi terjerumus ke dalam cahaya kelabu akibat kiamat. Bau darah belum hilang dan debu kehancuran perang terakhir belum juga mengendap, namun di laboratorium dan pabrik mereka sudah bekerja dengan kecepatan penuh lagi demi menjaga perdamaian dengan bantuan senjata yang bisa meledak. seluruh dunia.”
Karena kekerasan merupakan bentuk aktivitas yang ekstrem, kekerasan paling sering dirasakan tidak hanya pada tingkat kesadaran biasa, tetapi juga dalam sejumlah konsep ilmiah sebagai fenomena negatif apriori, yang sama sekali tidak sesuai dengan norma moral yang diterima secara umum. Pendekatan ini, yang beroperasi dengan nilai-nilai tertentu yang tidak dapat diubah dan bercirikan keterusterangan dogmatis, tidak memungkinkan kita untuk mempertimbangkan fenomena ini dalam konteks evolusi sejarah peradaban, untuk membedakan tindakan kekerasan yang secara kualitatif berbeda dalam isi dan tujuannya. Mengekspresikan sikap kritis terhadap pendekatan satu dimensi semacam ini, ilmuwan politik Amerika Charles Naiburg menulis: “Masyarakat terdiri dari masyarakat dan kelompok orang yang bersaing untuk mendapatkan atau mempertahankan berbagai manfaat dengan menggunakan berbagai cara. Dalam perjuangan ini digunakan cara-cara damai atau kekerasan, dan karenanya kehidupan masyarakat ditentukan oleh dua konsep - perdamaian atau perang, kekerasan atau non-kekerasan. Negara damai berarti persaingan terjadi dalam kerangka legalitas dan hukum. Sebaliknya, ketika tatanan yang ada dilanggar dan benturan kekuatan yang berlawanan mencapai tingkat yang sangat parah, perjuangan ini akan menghasilkan tindakan kekerasan.”
Aksioma yang ada mengenai pandangan kekerasan sebagai fenomena eksklusif antisosial dan ekstrakultural disebabkan oleh campuran dua pendekatan berbeda - historis-teoretis dan moral, yang beroperasi terutama pada kategori moral. Dalam kasus terakhir, tidak mungkin untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara kekerasan dan manifestasi lain dari aktivitas manusia, jenis organisasi sosial tertentu, dan untuk membangun korelasi dinamika evolusionernya. Mengabaikan prinsip historisisme dan karakter kelas dari hukum objektif pembangunan sosial mengarah pada fakta bahwa semua manifestasi kekerasan dianggap homogen. Hanya ketika menganalisis kekerasan dalam aspek sosiokultural barulah kita dapat menganggapnya sebagai bentuk kehidupan sosial transhistoris, suatu cara eksistensi manusia yang universal.
Sejarah mewakili arena konfrontasi antara kekuatan kreatif dan destruktif yang saling berhubungan secara dialektis; proses sejarah secara bersamaan dipengaruhi oleh faktor konstruktif dan destruktif. Dapat dimengerti bahwa subjek hubungan interpersonal memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap tindakan kekerasan, tergantung pada sisi “barikade sosial” mana mereka berada. Namun pada saat yang sama, kita pasti setuju dengan pemikiran yang diungkapkan oleh R. Aron bahwa “sejarah setidaknya tetap menjadi sejarah manusia yang berkembang hingga saat ini, ketika sejarah pada hakikatnya ditentukan oleh perjuangan dan kekerasan. Dan hal ini akan ditentukan oleh kekerasan sampai akhir zaman prasejarah,” yaitu sampai antagonisme antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam hilang.
Telah ditetapkan secara ilmiah bahwa dalam 3.400 tahun sejarah yang tercatat, hanya ada 234 tahun ketika manusia tidak berperang. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa perang bukanlah fenomena yang terjadi secara acak. Mereka tidak muncul sama sekali karena kemauan masing-masing penguasa atau karena ambisi ambisius para jenderal. Meskipun, tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan kasus-kasus ketika nafsu manusia lebih diutamakan daripada akal. Jika tidak, sejarah akan terlihat terlalu fatalistis. K. Clausewitz menganggap tidak masuk akal, karena rasa muak terhadap “beratnya elemen perang”, untuk melupakan sifat alami dan akar obyektifnya. “Perang adalah bagian dari kehidupan sosial,” tulisnya. “Perang adalah benturan kepentingan penting yang diselesaikan dengan pertumpahan darah, dan hanya dengan cara inilah perang berbeda dengan konflik lainnya.”
Kriteria yang menentukan untuk menetapkan signifikansi dan peran sebenarnya dari suatu tindakan kekerasan tertentu bukanlah moralnya, tetapi faktor esensialnya, yaitu tujuan yang dimaksudkan. Semuanya tergantung pada apakah kekerasan yang digunakan merupakan instrumen tirani atau demokrasi, instrumen penegakan hukum dan pembelaannya, atau pelanggarannya. Kekerasan dapat memainkan peran positif dan menjadi kebutuhan obyektif ketika penggunaannya berkontribusi pada kemajuan masyarakat, ditujukan terhadap penjajah asing, dan untuk menggulingkan rezim anti-rakyat. T. Jefferson percaya bahwa pemberontakan rakyat melawan penguasa yang tidak diinginkan adalah “hal yang baik dan sama pentingnya dalam dunia politik seperti halnya badai di alam. Pemberontakan ini mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan terjadinya pemberontakan."
Semua revolusi besar dalam sejarah, yang memainkan peran “lokomotif” kemajuan sosial dan menandai dimulainya tahap baru peradaban, terpaksa menggunakan kekerasan untuk melawan kekuatan konservatif. Komune Paris pada abad ke-19. dan revolusi sosialis di Rusia pada abad ke-20. – dua peristiwa penting ini, yang mempengaruhi pikiran banyak generasi, tidak hanya merupakan faktor destruktif, tetapi juga faktor kreatif.
Kekerasan sebagai metode pembelaan diri dan penyelamatan dari tindakan kekerasan agresif, sebagai cara untuk mencegahnya, diakui sah dan dapat dibenarkan. Perang pembebasan nasional tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan masing-masing negara, namun juga berkontribusi terhadap perlindungan dan penyebaran hak asasi manusia dan kebebasan universal; sistem kolonial runtuh karena serangan gencar mereka. Berkat kekalahan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II, umat manusia terselamatkan dari perbudakan fasis.
Manifestasi kekerasan sosial yang paling terkonsentrasi dan berskala besar adalah perang. Apa yang diciptakan selama bertahun-tahun oleh kerja manusia dan pikiran kreatif dihancurkan selama perang bersama dengan pencipta kekayaan material dan spiritual dan berubah menjadi reruntuhan. Pembayaran untuk perang yang dimulai meningkat sebanding dengan tingkat perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengenalan penemuan-penemuan mereka ke dalam bidang militer. Perang menjadi semakin berdarah dan merusak. Hampir 10 juta orang menjadi korban Perang Dunia Pertama, kerugian materi diperkirakan mencapai 338 miliar dolar. Lebih dari 54 juta orang tewas dalam Perang Dunia II, dan kerugian materi mencapai $4 triliun.
Tidak hanya “industri kematian” yang berkembang, tetapi teori militer, strategi dan taktik perjuangan bersenjata juga diubah sesuai dengan munculnya senjata tempur baru. “Pencapaian” terbaru dari pemikiran militer adalah “perang bebas risiko” yang telah dikembangkan dan digunakan dalam praktik. Doktrin “perang bebas risiko” yang menjadi andalan para jenderal Amerika merupakan produk inovasi teknologi, karena didasarkan pada kemampuan untuk menghindari risiko kerugian yang signifikan bagi negara yang memiliki keunggulan teknis militer mutlak dalam persenjataan. konflik yang ditimbulkannya. Atas dasar inilah pemerintah AS mengambil keputusan untuk menginvasi Irak, meyakinkan masyarakat akan impunitas praktis dari tindakan agresif ini bagi AS sendiri dan sekutu NATO-nya. Penilaian serupa dibuat selama agresi militer di Yugoslavia. Dinyatakan bahwa senjata terbaru memungkinkan untuk melakukan “serangan presisi” secara eksklusif terhadap sasaran militer, dan penggunaannya seharusnya tidak mengancam penduduk sipil.
Namun semua pernyataan tersebut ternyata hanya mitos dan terbantahkan oleh realitas realitas militer. Tidak ada perang yang “bersih”; perang selalu membawa kematian dan penderitaan bagi semua pihak yang terlibat, menyebabkan kehancuran materi dan kerusakan moral. Konsep perang “pertumpahan darah kecil” harus dianggap tidak manusiawi seperti bentuk apologetika lainnya terhadap militerisme. Namun militer juga dibedakan oleh egoismenya yang sinis dalam penafsirannya terhadap masalah keamanan, karena para propagandisnya mewakili kepentingan pihak yang berperang yang lebih dilengkapi dengan jenis senjata terbaru dan oleh karena itu terdapat risiko kematian massal personel militer. apalagi. Adapun kematian orang-orang di seberang sana, termasuk warga sipil, nasibnya rupanya tidak diperhitungkan sama sekali.
Saat ini, hanya ada satu negara adidaya di dunia - Amerika Serikat, dan tidak ada negara yang dapat menandinginya dalam hal kekuatan militer. Namun dalam konteks konfrontasi nuklir, ketika Rusia dan beberapa negara lain memiliki senjata pemusnah massal, superioritas Amerika dalam kekuasaan berubah menjadi ilusi. Jika terjadi konflik militer yang melibatkan penggunaan senjata rudal nuklir, Amerika Serikat menghadapi bahaya kehancuran yang sama seperti lawan-lawannya. Harga risiko menjadi sama bagi semua orang, dan oleh karena itu kebijakan “kesombongan kekaisaran” sama sekali tidak dapat dibenarkan.
Terorisme politik yang sedang mengalami kebangkitan telah menjadi momok umat manusia modern. Dihidupkan kembali dalam skala dan bentuk yang belum pernah terjadi sebelumnya, hal ini berubah menjadi fenomena planet dan penuh dengan makna sosial dan nasional yang baru. Perbedaannya dengan terorisme seabad yang lalu, yang sebagian besar digunakan oleh kaum revolusioner Rusia, terutama terletak pada sifat internasionalnya, dalam cakupan globalnya di seluruh wilayah di planet ini tanpa kecuali. Objeknya tidak lagi hanya individu saja, namun juga masyarakat luas, institusi publik dan pemerintah, sistem transportasi dan energi. “Hal baru dalam terorisme saat ini,” tulis filsuf Amerika O. Demaris, “adalah bahwa teroris telah membuang konsep orang yang tidak bersalah, mereka menyatakan hak untuk membunuh semua orang, dan berupaya meneror seluruh negara.” Metode yang tidak dikenal dalam terorisme “klasik”, seperti penyanderaan untuk tujuan politik, juga telah meluas.
Terorisme, seperti fenomena sosial lainnya, berasal dan dimotivasi oleh faktor politik, ideologi, ekonomi, etnis, dan agama. Hal ini merupakan cerminan, yang terdistorsi dalam esensi dan arah, mengenai keadaan penindasan dan kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar penduduk di beberapa wilayah di planet ini dan segmen masyarakat tertentu. Hal ini merupakan respons dendam mereka terhadap anggapan adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan materi antar kelas dan bangsa, hingga keengganan masyarakat kaya untuk berbagi dengan masyarakat miskin. “Terorisme tidak lahir dari ketiadaan. Ada alasan-alasan yang jarang membenarkan hal tersebut, namun selalu dapat menjelaskan hal tersebut,” kata ilmuwan politik asal Prancis, C. Julien, sambil menunjukkan bahwa kekerasan teroris, sebagai ledakan ketidakpuasan massal, memperjelas kelemahan-kelemahan masyarakat. Oleh karena itu, mereka berusaha mengoreksi satu kejahatan dengan kejahatan lainnya. Menyadari bahwa terorisme mencerminkan perlawanan sengit peradaban Timur terhadap serangan peradaban Barat yang dipersenjatai dengan pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang merusak, bahwa terorisme ditujukan untuk melawan kebijakan globalisasi yang kejam yang dilakukan demi kepentingan nasional dan perusahaan yang egois, filsuf Inggris C. Freeman menekankan bahwa “tujuan teror total yang benar” mengarah pada perampasan nyawa warga negara yang tidak terkait dengan pengambilan keputusan pemerintah dan tidak bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
Tujuan spesifik yang ingin dicapai ketika melakukan aksi teroris dapat sangat bervariasi. Peristiwa yang paling tidak terduga dan sulit diprediksi bisa menjadi penyebabnya. Gelombang protes disertai aksi kekerasan melanda dunia sehubungan dengan terbitnya karikatur Nabi Muhammad SAW di pers Barat. Fakta ini menunjukkan bahwa fenomena yang tampaknya tidak penting ini dari sudut pandang mentalitas Eropa dapat menimbulkan reaksi yang begitu besar dan akut dari umat Islam dan menjadi pemicu tidak hanya perang peradaban yang “dingin” tetapi juga “panas”.
Terorisme bersifat historis dan transnasional, dengan manifestasi spesifik di era berbeda dan di wilayah berbeda. Hal ini mengakibatkan kompleksitas pengetahuan ilmiah dan definisi aktivitas teroris, yang terkadang tidak sesuai dengan skala nilai dan norma yang berlaku umum, bersifat ambigu, dan seringkali dinilai dengan standar ganda. Oleh karena itu, jelas masih terdapat penafsiran yang sangat luas dan tidak jelas secara terminologis terhadap konsep “terorisme”, suatu kerancuan berbagai bentuk manifestasinya.
Yang perlu diperhatikan secara khusus adalah bahaya bentuk terorisme seperti terorisme negara, yang kini telah meluas. Hal ini terekspresikan dalam tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan kerugian material dan moral bagi negara, campur tangan yang melanggar hukum dalam urusan dalam negeri negara tersebut melalui penggunaan elemen oposisi yang menentang pemerintah yang sah, dan mencapai superioritas atas subjek hubungan internasional lainnya melalui cara ilegal lainnya. Terorisme negara, yang seringkali tersembunyi di balik slogan perjuangan demokrasi dan hak-hak sipil, telah menjadi metode utama tindakan agresif kebijakan luar negeri AS. Hal ini termasuk tindakan militer langsung oleh Amerika Serikat di Yugoslavia dan Irak, dan upaya untuk memberikan tekanan dalam berbagai bentuk terhadap Rusia dan negara-negara CIS lainnya.
Tidak mungkin untuk mengakui validitas penjelasan terorisme yang ada hanya karena kelemahan patologis dalam jiwa individu, kehadiran orang-orang yang bersifat agresif, yang dalam kode biologisnya terdapat “gen agresi”, yang dikuasai oleh kekuatan. “refleks ketidaktaatan”. Teroris tidak dilahirkan, mereka berada dalam kondisi sosial tertentu yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku individu yang mengambil jalur tindakan ilegal dan tidak bermoral, didukung oleh argumen teoretis dan slogan politik yang salah. Di antara para teroris tentunya banyak terdapat orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan gangguan jiwa, yang jumlahnya semakin meningkat saat ini, hal ini disebabkan oleh meningkatnya situasi stres dan kejadian ekstrim yang menyebabkan meningkatnya tekanan psikologis pada seseorang. Kita bisa sepakat dengan pendapat bahwa terorisme politik adalah produk sampingan dari revolusi industri, kekacauan yang diakibatkan oleh penghancuran pola hidup lama. Runtuhnya struktur sosial dan revaluasi nilai-nilai yang terjadi pada masa transisi membuat strata sosial penting tersingkir dari kehidupan sehari-hari dan berujung pada deklasifikasi, sehingga menimbulkan perasaan terhina dan putus asa, serta manifestasi ekstremisme yang ekstrem. Namun menarik kesimpulan umum mengenai kondisi mental semua teroris berdasarkan hal ini tampaknya tidak dapat dibenarkan.
Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa komposisi sosial organisasi teroris sangat heterogen. “Déclassé dan perasaan kekurangan yang diakibatkannya, reaksi menyakitkan terhadap ketidakadilan, kebencian terhadap realitas di sekitarnya, kehausan akan balas dendam dan penegasan diri, gagasan primitif tentang kebebasan dan kesetaraan dengan mudah mengarah pada gagasan penyangkalan total dan merangsang keinginan. untuk tindakan destruktif. Aspirasi tersebut dapat diwujudkan dalam kerusuhan massal dan tindakan yang bersifat kriminal. Namun mereka juga mampu dihiasi dengan penderitaan perjuangan anti-kapitalis dan bahkan perjuangan demi cita-cita sosialis.”
Dengan demikian, keunikan fenomena terorisme justru terletak pada kenyataan bahwa ia erat kaitannya dengan individualisme romantis dan petualangan politik, aspirasi terhadap cita-cita yang lebih tinggi dan kekejaman fanatik yang tidak bermoral, kepercayaan pada pilihan dan ketidakberprinsipan diri sendiri, pengorbanan yang menyimpang dan inferioritas patologis, campuran dari yang nyata dan diinginkan.
Praktik sejarah dengan cukup meyakinkan mengungkap ketidakefektifan dan bahaya aksi teroris sebagai sarana perjuangan revolusioner dan pembebasan nasional. K. Marx, yang mengklasifikasikan terorisme sebagai manifestasi dari kesukarelaan dan petualangan politik, mencirikannya sebagai “khayalan sejarah dunia” yang menjadi sasaran beberapa pejuang “kebaikan umat manusia”. Tidak ada rujukan pada tujuan baik tertentu yang menjadi dasar dilakukannya tindakan teroris yang dapat dijadikan pembenaran. Hal-hal tersebut mau tidak mau terkait dengan pelanggaran norma legalitas dan moralitas, mengancam kebebasan dan keselamatan masyarakat, hak asasi manusia - hak untuk hidup, dan tidak sesuai dengan prinsip humanisme. “Suatu tujuan yang membutuhkan cara yang salah bukanlah tujuan yang benar…” Kita tidak boleh lupa bahwa kekerasan melahirkan kekerasan, hal ini selalu menimbulkan reaksi berantai dan mau tidak mau berujung pada kekerasan pembalasan.
Terorisme tentu saja merupakan fenomena sosial yang ditentukan oleh kondisi obyektif keberadaan sosial. Kegagalan untuk mengakui kebenaran ini dan mengabaikan keberadaan faktor-faktor nyata yang memicu terorisme menghambat perjuangan yang konsisten melawan terorisme. Namun, di sisi lain, seseorang tidak boleh berbagi ide-ide reproduksionis yang vulgar tentang sifat dasar kejahatan yang tidak dapat direduksi, keniscayaannya yang mutlak. Kita pasti setuju dengan pendapat sejumlah ilmuwan tentang kemungkinan mengatasi fenomena yang tidak diinginkan ini, tetapi hanya jika kita tidak mendukung keyakinan bahwa agresivitas adalah naluri biologis yang tidak dapat direduksi.
Rusia kini kembali mengalami perubahan tonggak sejarah. Proses reformasi terjadi dalam kondisi realitas pasca-Soviet yang sulit, disertai dengan benturan antara cara hidup baru dan cara hidup lama yang tidak terburu-buru untuk ditinggalkan, dan konfrontasi berbagai kekuatan sosial. “Topan” dari segala jenis krisis, kejahatan, dan konflik antaretnis melanda Rusia. Bukan suatu kebetulan bahwa Rusia dianggap oleh para ahli internasional sebagai “zona berisiko tinggi.” Dalam suasana ketidakstabilan dan konflik yang meningkat, ada kecenderungan untuk mengejar politik kekuasaan, keinginan untuk menggunakan metode diktator untuk memulihkan ketertiban dan segera keluar dari krisis, nostalgia akan “tangan yang kuat” muncul, dan “elang politik” meningkatkan kekuatan mereka. kepala.
Bagi Rusia, masalah kekerasan telah menjadi salah satu masalah yang paling penting dan penting sepanjang sejarah. Ada banyak stereotip yang dibuat secara artifisial dan bersifat negatif tentang “kekerasan Rusia” dalam kesadaran publik dunia. Merupakan kebiasaan untuk menggambarkan Rusia sebagai kekuatan agresif utama di arena internasional dan mengaitkannya dengan tradisi pembangunan ekspansionis dengan tujuan menaklukkan seluruh dunia. Dan saat ini terdapat argumen bahwa, terlepas dari transformasi demokrasi apa pun, masyarakat Rusia terus menunjukkan “kekerasan total” terhadap individu, sebuah ancaman terhadap kebebasan universal dan demokrasi. Di balik semua sindiran ini tersembunyi tujuan jangka panjang musuh-musuh Rusia. Sejarawan Rusia K.S. Aksakov pada abad ke-19. menulis bahwa jika sebuah kampanye diluncurkan di suatu tempat untuk menuduh Rusia melakukan kebijakan agresif, ini berarti salah satu negara Barat sedang bersiap untuk melakukan agresi lain di suatu tempat. Kebenaran penilaian ini ditegaskan oleh kenyataan saat ini. Sebelum invasi AS ke Yugoslavia dan Irak, kampanye propaganda anti-Rusia diluncurkan di Barat.
Fenomena “kekerasan Rusia”, yang memiliki ciri universal dan sifat umum dari esensi substantif yang melekat pada kekerasan sebagai kategori sosial-politik, sekaligus memiliki ciri dan perbedaan tersendiri. Hal ini ditentukan oleh realitas sejarah dan geopolitik tertentu, hubungan sosio-ekonomi yang berlaku, dan mentalitas Rusia yang spesifik. Beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan politik kekuasaan tradisional dan sifat despotik kekuasaan di Rusia dengan berbagai macam penyimpangan patologis dalam jiwa individu politisi Rusia dan sifat subjektif para penguasanya. Mungkin dalam beberapa kasus hal ini benar-benar terjadi, namun faktor obyektif masih memainkan peran yang menentukan di sini. Pertama-tama, seperti kebutuhan untuk “mengumpulkan tanah Rusia”, menghilangkan fragmentasinya, dan menyatukan banyak kerajaan menjadi satu kesatuan. Kekejaman keadaan mendikte perlunya sistem pemerintahan negara yang otoriter dan terpusat secara maksimal, perlunya mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan swasta, regional, dan individu.
Terletak di antara Timur dan Barat dalam aspek geografis dan peradaban, Rusia harus menanggung lebih banyak bencana militer dibandingkan negara lain, dan terus-menerus mempertahankan wilayahnya dari agresor asing. Dalam 538 tahun yang berlalu sejak Pertempuran Kulikovo hingga keluarnya Rusia dari Perang Dunia Pertama, Rusia berperang selama 334 tahun, yaitu dua pertiga dari kehidupan historisnya. Semua modernisasi sosial berskala besar dilakukan di Rusia “dari atas”, dan, biasanya, disertai dengan penggunaan kekerasan massal. Metode “kekerasan reformasi” digunakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan budaya dalam setiap upaya untuk “memotong jendela” ke dalam peradaban Barat.
Skala wilayah Rusia dan keragaman masyarakat yang menghuninya, ketidaktaatan para pemimpin regional dan kebijakan separatis mereka juga sangat menentukan bentuk dan metode pemerintahan otoriter. Prinsip persatuan dan kesatuan Rusia dipertahankan dengan ketat dan dilaksanakan dengan segala cara yang mungkin, dan selalu menjadi prinsip fundamental yang dominan di antara semua penguasa Rusia. Dan ada penjelasan untuk ini. Mengekspresikan sikap negatif terhadap manifestasi separatisme dalam kondisi Rusia revolusioner dan menunjukkan keterlibatan kekuatan eksternal yang bermusuhan dalam fenomena ini, Alexander Blok menulis bahwa “jika Rusia bubar”, maka akhir dari kekuatan besar akan datang, itu akan terjadi. menjadi pelayan entitas negara yang kuat. Benar-benar cerdas.
Akhir abad ke-20 ditandai dengan berkuasanya kekuatan politik baru di Rusia yang mengandalkan pelaksanaan reformasi demokrasi dan penghapusan masa lalu totaliter. Sasaran strategis dari proses modernisasi menyeluruh yang telah dimulai dicanangkan adalah pembangunan masyarakat sipil dan supremasi hukum, ekonomi pasar, dan menjamin prioritas hak asasi manusia dan kebebasan. Namun, “pawai kemenangan” demokrasi belum terjadi. Hal ini tidak dapat diharapkan, berdasarkan pada pola historis umum dari proses reformasi, serta beberapa ciri “individu” dari realitas Rusia. Praktek dunia dalam pembentukan dan pengembangan demokrasi menunjukkan bahwa proses ini tidak pernah berlangsung dengan cepat, mudah dan bebas konflik. Pengenalan nilai-nilai demokrasi ke dalam kesadaran publik dan praktik politik tidak dapat dicapai dengan “tuduhan kavaleri”.
Demokrasi belum menjadi norma dan pandangan hidup masyarakat dan warga negara, nilai-nilai demokrasi masih belum terwujud. Anti-humanisme totaliter digantikan oleh anti-humanisme pasar; alih-alih kediktatoran para pemimpin partai, yang muncul adalah dominasi bisnis kriminal dan birokrasi yang korup, pelanggaran hukum yang merajalela, dan keadaan anarki. Namun bahkan T. Hobbes mengutarakan pendapatnya bahwa “lebih baik tinggal di negara yang tidak mengizinkan apa pun menurut hukum daripada di negara yang segala sesuatunya diperbolehkan menurut hukum”.
Terlepas dari situasi sosial-politik yang kacau dan tidak stabil, perpecahan masyarakat dan ketidakpuasan umum, Rusia tidak jatuh ke dalam pusaran perang saudara, perkembangan evolusioner yang damai tidak berubah menjadi bencana revolusioner yang tidak damai. Secara umum, proses modernisasi, terlepas dari segala kontradiksi dan konsekuensinya, berlangsung tanpa kekerasan. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih pantas dalam hal ini - pihak berwenang atau rakyat. Bagaimanapun, masyarakat tidak menanggapi “terapi kejut” dengan “operasi kejut”, sehingga mereka berhasil menghindari “pertumpahan darah besar-besaran”.
Namun, ternyata masih mustahil untuk menggerakkan sejarah Rusia ke jalur baru perkembangan peradaban hanya melalui cara-cara damai, tanpa menghindari kekerasan sama sekali. Contoh di Rusia sekali lagi menegaskan kebenaran pemikiran P. Sartre bahwa kekerasan bagaimanapun juga diperlukan untuk berpindah dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Awal mula proses perestroika ditandai dengan sejumlah konflik yang disertai aksi kekerasan dan bentrokan bersenjata di negara-negara Baltik, Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Moldova. Beberapa di antaranya dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, setelah runtuhnya Uni Soviet, dengan partisipasi Rusia, yang karena satu dan lain hal terpaksa mengirim kontingen militernya ke “titik panas” CIS ini.
Namun di Rusia sendiri, selama bertahun-tahun sejak awal reformasi, cukup banyak terjadi manifestasi kekerasan dalam berbagai bentuk dan alasan yang berbeda-beda. Kekuatan militer harus digunakan pada tahun 1991 untuk menekan konspirasi terkenal dari penyelenggara Komite Darurat Negara, yang bertujuan untuk mengubah kepemimpinan negara dan memperbaiki kebijakan perestroika M. S. Gorbachev. Dan meskipun hanya terjadi “sedikit pertumpahan darah” di sini, ibu kota Rusia saat ini menyerupai kota militer. Perjuangan bersenjata antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, ketika tentara reguler berpihak pada yang pertama, dan yang terakhir didukung oleh sukarelawan yang mewakili kekuatan oposisi, terjadi pada tahun 1993. Peristiwa tragis ini, yang berakhir dengan penembakan terhadap orang Rusia parlemen dan menimbulkan banyak korban, belum menerima penilaian yang jelas, belum ada diskusi tentang pelaku sebenarnya dan legalitas tindakan pihak berwenang serta kemungkinan untuk menghindari penghentian pertumpahan darah.
Bukan tanpa perang lokal Rusia, yang dimulai di Chechnya pada tahun 1996 dan berlanjut hingga hari ini. Dengan kedok slogan Wahhabi tentang perjuangan “kemurnian Islam”, militan Chechnya, dengan dukungan aktif dari luar negeri, mengejar tujuan jangka panjang dengan memisahkan wilayah selatan yang luas dari Rusia dan menciptakan negara Islam bertipe fundamentalis. mereka. Setelah kehancuran kekuatan utama kelompok bersenjata ilegal, perang berpindah ke tahap perang gerilya di pihak mereka, yang menyebabkan kerugian besar, termasuk di kalangan penduduk sipil.
Banyak manifestasi aksi kekerasan dalam berbagai bentuk yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir “dari bawah”, yang dilakukan oleh masyarakat sipil, yang merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Kerusuhan dan pemogokan secara berkala terjadi di berbagai wilayah di Rusia karena keterlambatan pembayaran gaji, pengangguran massal, pemadaman listrik, dan kesewenang-wenangan administrasi perusahaan dan pejabat pemerintah. Kerumunan pengunjuk rasa memblokir jalan raya dan kereta api, mengepung lembaga-lembaga pemerintah, dan menahan karyawan mereka sebagai sandera. Seringkali gerakan protes massal ini disertai dengan penggunaan kekuatan fisik dari kedua belah pihak.
Namun jika manifestasi kekerasan terbuka pada masa transisi ini relatif terbatas, maka hal yang sama mungkin tidak dapat dikatakan mengenai manifestasi kekerasan terselubung, yang tidak begitu mencolok dan bersifat lebih terselubung. Kekerasan laten tersebut, termasuk tindakan yang menyebabkan kerugian dan kerugian tidak hanya secara fisik, tetapi juga pemaksaan ekonomi, ideologi dan psikologis tidak langsung, manipulasi kesadaran dan perilaku masyarakat, mempunyai bahaya yang sama dengan kekerasan fisik langsung. Tentu saja, kita berhak memasukkan demonstrasi kekerasan tidak langsung yang dilakukan di Rusia pada tahun 90an. privatisasi skala besar, yang menyebabkan kerugian material dan moral yang sangat besar bagi masyarakat pada umumnya dan warga negara pada khususnya. Redistribusi properti secara menyeluruh, yang pada dasarnya mengakibatkan perampasan properti publik secara ilegal oleh sekelompok pengusaha yang tidak jujur dan pejabat korup, penerapan harga bebas yang tidak terkendali, runtuhnya tabungan moneter penduduk, dan inflasi raksasa yang terjadi kemudian menyebabkan banyak malapetaka. orang-orang menuju kehidupan yang menyedihkan. Bahkan menurut statistik resmi, seperempat penduduk negara ini hidup dengan pendapatan di bawah tingkat subsisten. Dalam kondisi tersebut, timbul masalah ketimpangan antara “kesetaraan kesempatan” dan “kesetaraan hasil”, yaitu perbedaan antara hak dan kebebasan konstitusional formal warga negara dan pelaksanaan praktisnya, yang bergantung pada kondisi sosial. status ekonomi individu. Dalam masyarakat yang menerapkan reformasi demokrasi, dalam praktiknya seseorang akan merasa terasing dibandingkan dengan masyarakat totaliter komunis.
Peningkatan tajam angka kematian yang terjadi di Rusia dalam beberapa tahun terakhir, yang mencapai satu juta orang setiap tahunnya, tidak diragukan lagi sebagian besar disebabkan oleh kekurangan gizi dan perawatan medis bagi sebagian besar penduduk. Stres mental meningkat akibat perasaan terhina, putus asa, dan pesimisme yang mencengkeram masyarakat. Yang juga merupakan indikasi adalah fakta peningkatan angka bunuh diri yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam hal jumlah kasus bunuh diri yang menduduki peringkat pertama Rusia dalam statistik dunia. Pertumbuhan semua jenis kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama kejahatan terorganisir, yang korbannya mencapai puluhan ribu orang setiap tahun, juga dapat dikaitkan dengan manifestasi perang sosial virtual di masyarakat.
Cara berpikir dan perilaku manusia modern sangat bergantung pada pengaruh media terhadap dirinya. Dengan menggunakan teknologi komunikasi terkini, mereka mampu melakukan kekerasan moral dengan memanipulasi kesadaran publik ke arah tertentu, melakukan tujuan disinformasi dan korupsi spiritual massa, dan mengubah masyarakat menjadi massa yang tidak berpikir dan patuh. Kekerasan informasi dan psikologis terhadap warga negara Rusia dilakukan dengan kedok kebebasan berpendapat oleh media, yang menanamkan kultus kekerasan, sikap permisif, dan amoralitas. Kaki tangan mereka dalam hal ini adalah budaya massa dasar, yang menghasut perasaan rendahan dan mendorong kecenderungan jahat, merusak generasi muda Rusia. Mencari sensasi yang tidak sehat, media mengarahkan kesadaran masyarakat pada citra konsumen, menanamkan sikap hedonistik dan prinsip individualisme egois, serta melakukan manipulasi total terhadap khalayak, menggantikan yang nyata dengan yang virtual secara simbolis.
Apakah penolakan secara umum terhadap peperangan dan penggunaan kekerasan mungkin dilakukan, dan dapatkah “perdamaian abadi” dicapai? Hal ini bergantung pada faktor sosiokultural yang kompleks, apakah norma perdamaian akan menjadi hukum tertinggi dalam hubungan tidak hanya antar manusia, tetapi juga antar negara. Budaya perdamaian harus berubah menjadi kebutuhan sejarah dan menjadi dominan dominan umat manusia di abad ke-21.
Jika perpecahan umat manusia yang bermusuhan, ketidakcocokan peradaban yang berlawanan tidak diatasi, dan keinginan untuk mencapai superioritas seseorang dengan kekerasan tidak diakhiri, pedang Damocles dari bencana militer global akan terus menghantui umat manusia. Perang sosial harus dilawan dengan perdamaian sosial. Patut diasumsikan bahwa gagasan “perdamaian abadi” bukanlah utopia mutlak, melainkan utopia relatif. Meskipun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi saat ini, namun bukan berarti hal tersebut tidak akan pernah dapat dilaksanakan. Bagaimanapun, sejarah adalah proses perubahan terus-menerus dalam kondisi keberadaan dan sifat manusia, transformasi utopia menjadi realitas praktis. Dan karena, seperti yang diyakini Teilhard de Chardin, “sejarah kehidupan pada dasarnya adalah perkembangan kesadaran,” ada kemungkinan bahwa pada titik tertentu dalam proses evolusi ini, di bawah pengaruh keadaan tertentu, lompatan kualitatif dalam pemikiran manusia akan terjadi, menandai perubahan dari budaya kekerasan ke budaya non-kekerasan.
V.I. Vernadsky, dengan mempertimbangkan tren globalisasi yang berkembang dengan manifestasinya yang kontradiktif, menyatakan keyakinannya bahwa umat manusia mampu bertahan hanya dengan belajar berpikir dalam kategori kosmik. Untuk melakukan hal ini, setiap penghuni planet ini harus “berpikir dan bertindak dalam aspek baru, tidak hanya dalam aspek individu, keluarga atau klan, negara atau persatuan mereka, namun dalam aspek planet.” Filsafat perdamaian harus menjadi bentuk pemahaman sehari-hari tentang dunia, berubah menjadi cara orientasi intrakultural seseorang, dan menjadi matriks intelektual era sejarah baru yang diakui secara umum. Karena seseorang adalah produk dari keadaan sosial tertentu, untuk mengubah kesadaran dan perilakunya, keadaan tersebut harus diubah dan dijadikan manusiawi.
Saling pengertian dan kepercayaan merupakan faktor utama dalam globalisasi masyarakat dunia dan dalam membangun dunia tanpa kekerasan berdasarkan solidaritas kemanusiaan. Dialog bebas mengenai isu-isu utama saat ini menjadi penting. Melalui pendekatan ini, tidak hanya permasalahan hubungan internasional terkini yang diidentifikasi dan diselesaikan, namun juga prospek pembangunan global, dan peluang untuk menghindari bentuk-bentuk konfrontasi yang ekstrim.
Proses progresif perkembangan peradaban, orientasinya yang umumnya progresif, memberikan dasar bagi optimisme, dan tidak ada perang pemusnahan dan bencana alam yang merusak, tidak ada pergolakan revolusioner dan zigzag geopolitik yang dapat menggoyahkan keunggulan cita-cita humanistik, kehidupan di atas kematian, atau menghentikan keinginan yang tak tertahankan untuk hidup. orang untuk menemukan kehidupan duniawi yang damai dan bahagia. Dan mungkin di abad ke-21. Impian penyair Rusia Sergei Yesenin tentang saat “ketika permusuhan suku akan terjadi di seluruh planet” akan menjadi kenyataan.
Kata kekerasan mempunyai akar kata yang sama dengan kata kekuatan. Kekerasan adalah fakta kehadiran dan penggunaan atau manifestasi kekuatan. Dan jika pertanyaannya adalah – bagaimana perasaan Anda tentang kekerasan? - secara umum, jawaban negatif muncul dengan sendirinya, lalu untuk pertanyaan - bagaimana perasaan Anda tentang kekuatan? - jawabannya sepertinya tidak begitu jelas. Karena lawan dari kekuasaan adalah ketidakberdayaan, bukan moralitas atau kebaikan. Dan jika kekuasaan itu jahat, maka ketidakberdayaan bukanlah nilai positif.
“Saya tidak suka kekerasan dan ketidakberdayaan,” Vladimir Vysotsky pernah bernyanyi. Dan dalam perkataannya kita dapat merumuskan suatu masalah filosofis yang signifikan. Kedua situasi ini - kehadiran dan penggunaan kekuatan, serta ketidakhadirannya, sebenarnya menghabiskan semua kemungkinan situasi kehidupan, terutama yang timbul dalam keadaan force majeure. Kekerasan dapat dianalisis, di satu sisi, dalam konteks bentuk dan metode pendidikan dan pengasuhan, dan di sisi lain, sebagai salah satu tema atau subjek refleksi, sebagai subjek terpenting dalam pandangan dunia apa pun.
Masalah kekerasan dapat diselesaikan bukan dari sudut pandang filsafat moralistik, tetapi dari sudut pandang filsafat kehidupan. Hidup adalah semacam proses kekuatan, benturan terus-menerus dengan kekuatan orang lain, serta manifestasi dari kekuatan atau ketidakberdayaan diri sendiri untuk melawan kejahatan.
Pada tahun 1925, filsuf Rusia Ivan Ilyin menerbitkan buku berjudul “On Resistance to Evil by Force.” Dalam dunia modern yang penuh dengan serangan teroris dan operasi anti-teroris, yang sering dijadikan lelucon sedih bahwa tindakan tersebut selalu dilakukan tanpa anestesi, filosofi Ilyin ternyata sangat relevan.
Para filsuf sering menggambarkan kehidupan sebagai proses yang penuh kekuatan, namun mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Filsafat Eropa Nietzsche adalah filosofi kekuatan, sinonimnya dengan kehidupan, kepolosan dan kekebalan moral, prioritas dan keunggulan elit dari agresivitas ofensif dibandingkan dengan kepasifan, kelemahan, dan kurangnya vitalitas. Gagasan Rusia tentang Ivan Ilyin tidak terbentuk di luar kebaikan dan kejahatan, seperti Nietzscheanisme. Ini mewakili kombinasi langka antara filosofi perlunya menggunakan kekuatan dan filosofi moralitas yang dipahami secara agama. Bagaimana kombinasi ini dicapai?
Victor Hugo berkata: bagi saya tidak masalah pihak mana yang kuat, yang penting bagi saya adalah pihak mana yang benar. Di luar mentalitas hukum Eropa, dalam bahasa Rusia dirumuskan sebagai berikut: Tuhan tidak berkuasa, tetapi dalam kebenaran, kedengarannya indah dan menyedihkan. Namun saya tetap ingin mempertahankan pentingnya pertanyaan mendasar: Di pihak manakah kekuasaan berada? Siapa yang akan dia ambil? Siapa yang akan menang? Benar, kebenaran, kebaikan, keadilan atau kejahatan, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan? Manakah dari dua pihak yang berlawanan ini yang akan lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bersifat retoris, tetapi bersifat praktis dan tajam. Lagi pula, kita tidak berjuang demi impotensi kebaikan, demi kekalahan tujuan yang adil.
Sulit menjadi kuat bukan hanya karena lemahnya kemauan dan karakter. Menjadi kuat itu sulit karena alasan moral. Pemaksaan mempunyai kelemahan moral dan pilihan pemaksaan selalu merupakan pilihan rasa bersalah.
Kompleksitas hidup selalu merupakan kompleksitas pilihan. Pertama, kita membuat pilihan antara strategi kekerasan, dan oleh karena itu tindakan penggunaannya, dan strategi non-kekerasan, yang mungkin merupakan kelemahannya. Pemerkosa atau pecundang abadi? Setuju bahwa pilihan itu tidak menyenangkan. Kedua, kita memilih posisi itu sendiri, sisi perjuangan di mana kita akan menunjukkan kekuatan kita atau tidak menggunakannya.
“Hidup berarti berdiri di bawah semacam panji dan mengambil posisi bertarung,” tulis Ortega y Gasset dari Spanyol. Hidup membutuhkan keberanian, keterlibatan, komitmen. Kita berpartisipasi dalam kehidupan sejauh kita menerima dilema yang berat. Kebebasan memilih tidak terletak pada beragamnya pilihan yang diinginkan, tidak menyakitkan, dan ideal. Suatu ketika seorang ilmuwan politik yang berbicara di salah satu simposium universitas St. Petersburg mengungkapkan keraguan yang sangat umum tentang kemungkinan kebebasan memilih politik dalam masyarakat Rusia modern. Logikanya bermuara pada kenyataan bahwa di antara para pemimpin, kandidat, dan program reformasi tidak ada yang sempurna. Ia merumuskannya sebagai berikut: tidak ada kebebasan yang sesungguhnya, karena kita diminta untuk memilih antara wabah atau kolera. Salah satu peserta diskusi langsung bereaksi: Kami memilih kolera! Ada pilihan di sini! Kebijaksanaan filosofisnya adalah bahwa hidup berarti selalu siap untuk memilih antara wabah atau kolera. Inilah kebebasan sejati, kehidupan nyata, dan pilihan nyata. Dan pilihan ini tidak hanya harus tepat, tetapi juga menentukan. Jika kita tidak segera memilih untuk menangani kolera, maka wabah penyakit akan datang - bencana terburuk. Dan kami akan bersalah dalam hal ini. Episode pertentangan pendapat yang luar biasa ini menunjukkan bahwa keadaan yang sama dapat ditafsirkan sebagai pilihan yang bertanggung jawab bagi sebagian orang dan sebagai pilihan yang tidak bertanggung jawab bagi orang lain.
Jika hidup adalah sebuah perjuangan, dan ini adalah definisi favorit kita tentangnya, maka jelaslah bahwa perjuangan ini harus selalu berupa perjuangan untuk sesuatu dan melawan sesuatu. Kalau tidak, energi kehidupan, aktivismenya, tidak mungkin terjadi. Dalam banyak kasus, ini berarti kebutuhan untuk memilih salah satu dari dua pihak yang berlawanan, ketidakmungkinan sisi ketiga dari mata uang - posisi mengambang bebas di atas keributan dan kecaman moral atas tindakan lawan sebagai tindakan yang cacat. Upaya untuk memilih kepolosan imajiner adalah pelarian dari kehidupan yang tak terhindarkan. Kebetulan posisi kekuatan ternyata jauh lebih berharga dan berani daripada posisi kemarahan moral dalam penggunaannya. Saya teringat suasana Oktober 1993 sepuluh tahun lalu. Pada bulan Agustus 1991, selama kudeta pertama dan lebih tak berdarah, mayoritas penduduk, jika bukan seluruh Rusia, maka kota-kota metropolitan di ibu kota, menunjukkan keterlibatan aktif dalam bentrokan kubu politik yang sedang berlangsung. Hal itu diungkapkan dalam menentukan posisi seseorang dan kesiapan untuk mempertahankannya dengan mempertaruhkan nyawa. Hari-hari kudeta tahun 1993 di bulan Oktober memenuhi gelombang udara media kita dengan wawancara-wawancara monoton yang tak ada habisnya dengan banyak orang terkenal, yang nada umumnya adalah mengutuk kedua belah pihak karena menggunakan kekerasan, menempatkan diri mereka di luar konflik sosio-historis, dan bahkan di luar konflik sosio-historis. rumusan langsung dari prinsip Shakespeare “wabah di kedua rumah Anda.” " Seni kemurnian moral, kepolosan, dan pantangan ini sangat kuat justru di kalangan kaum intelektual, baik yang liberal dan berpikiran hak asasi manusia ala Barat, atau melanjutkan tradisi Tolstoyisme Rusia.
Berkaitan dengan itu, perlu diintensifkan warisan polifonik pemikiran moral dan politik Rusia, segala ambiguitasnya, yang diwujudkan dalam polemik Ivan Ilyin dengan Leo Tolstoy.
Ilyin mengkualifikasikan gagasan Tolstoy tentang tidak melawan kejahatan dengan kekerasan sebagai “egosentrisme moral yang halus”. Halus dan bermoral, karena ini adalah jalan peningkatan moral individu, bahkan rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain. Singkatnya, kemampuan untuk melakukan tindakan apa pun yang bernilai moral. Dan egoisme, karena altruisme, pengorbanan diri, penyangkalan diri dan pelupaan diri, yang merupakan hakikat cinta, tidak dilakukan tanpa batas dalam praktik moral Tolstoyisme. Penganut sejati Tolstoyisme hanya mampu melakukan pengorbanan yang lebih kecil - nyawanya, demi cinta kepada orang lain dan menyelamatkannya dari kekerasan - nyawanya, tetapi bukan pengorbanan yang lebih besar - kebenaran atau ketidakberdosaannya.
Novel terkenal Amerika karya William Styron, Sophie's Choice, yang difilmkan dengan Meryl Streep sebagai pemeran utama, mencontohkan situasi seperti ini. Selama Perang Dunia Kedua, seorang fasis Jerman mengajukan lamaran berikut kepada seorang wanita yang tiba di kamp konsentrasi bersama dua anaknya. Entah kedua anaknya, seperti anak lainnya, akan dikirim ke kehancuran, karena, tidak seperti orang dewasa, mereka tidak cocok untuk bekerja, atau salah satu dari mereka masih akan selamat. Kondisi yang mengerikan untuk kemungkinan menyelamatkan nyawa seorang anak adalah bahwa sang ibu sendiri harus memilih dan menunjukkan yang mana di antara keduanya, siapa yang sekarang, atas kemauannya, harus mati. Hal ini bahkan lebih buruk dibandingkan pilihan antara wabah dan kolera. Apa yang ditawarkan adalah keterlibatan dalam kejahatan, kejahatan, kekerasan, keterlibatan dalam pembunuhan bukan terhadap musuh untuk membela diri, melainkan terhadap anak sendiri. Seseorang dapat menolak - ini adalah pilihan bebas - tetapi harga yang lebih rendah untuk menyelamatkan setidaknya satu makhluk kesayangannya dalam situasi kritis ini tidak dapat dibayar. Ya, kejam, mengerikan, tak terpikirkan, tak tertahankan. Namun sudah tidak mungkin lagi berdiri di luar keadaan saat ini. Yang tersisa hanyalah membuat pilihan antara anak-anak atau menolak memilih, yang juga akan menjadi keputusan yang harus Anda tanggung. Dan tokoh utama dalam novel, yang tenggelam dalam kehidupan nyata, memilih kehidupan yang lebih tua dari keduanya. Namun dalam karya Tolstoy kita tidak akan menemukan analisis mengenai keadaan seperti itu; ini bukanlah perspektif yang digunakannya dalam memandang hubungan antarmanusia.
Apa sifat anti-egois dari filosofi memerangi kejahatan dengan kekuatan Ivan Ilyin? Bagaimana filosofi cinta berubah menjadi filosofi kekuatan? Pilihan dibuat bukan demi kebaikan diri sendiri, tapi demi kebaikan orang lain. Tawar-menawar, seperti yang mereka katakan, tidak pantas dalam kasus seperti itu. Ini bukan tentang perhitungan moral: lebih baik memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan. Kita berbicara tentang preferensi altruistik untuk menyelamatkan kehidupan fisik orang lain dengan mengorbankan kehancuran integritas moral seseorang.
Masalah dengan cita-cita berpakaian putih dan tangan bersih bukanlah kurangnya keindahan, tetapi gagasan utopis tentang kemandulan moral. Dalam kehidupan nyata, terus-menerus memilih sisi ketiga dari mata uang tidak masuk akal. Hidup ini rumit karena ketika memilih di antara berbagai kemungkinan, kita sering kali tidak memilih antara yang baik dan yang jahat, dosa dan kebenaran, tetapi memilih antara satu kejahatan dan yang lain, antara rasa bersalah karena melawan kejahatan dengan kekerasan dan rasa bersalah karena diam-diam, menurutinya dengan cara yang tidak baik. perlawanan. Bukan tanpa alasan asas hukum kelambanan pidana itu ada dan berlaku. Kembali ke alur cerita Styron, misalkan pahlawan wanitanya menolak untuk memilih di antara anak-anaknya, siapa di antara mereka yang harus hidup dan mana yang harus mati. Apakah dia akan menghindari keterlibatan dalam kejahatan dalam kasus ini? Tidak, dia tidak akan menyelamatkan anak-anaknya, atau kemurnian moralnya sendiri. Hanya ukuran dan bentuk kesalahannya saja yang berbeda. Ini akan terdiri dari pengorbanan moral yang tidak memadai.
Hanya orang kuat yang mampu melawan kejahatan, menggunakan kekerasan dan merasa bersalah. Yang lemah akan mencari alasan untuk dirinya sendiri. Pahlawan wanita Styron, yang tidak mengetahui apa pun tentang nasib masa depan putra yang dia selamatkan dan dengan demikian tidak memiliki konfirmasi apa pun atas pembenaran tindakannya, bunuh diri beberapa tahun setelah perang berakhir. Kesimpulan logis dalam hidupnya tidak boleh dilihat sebagai tanda kelemahan. Sebaliknya, hal itu harus dianggap sebagai wujud kekuatan batin untuk memberikan penilaian moral yang sempurna yang tidak disesuaikan dengan keadaan. Dengan demikian, filosofi yang membuktikan keniscayaan keterlibatan dalam kekerasan ternyata adalah filosofi rasa bersalah, bukan filosofi perjuangan menyelamatkan orang lain.
Tidak perlu berharap untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, kata Jean Paul Sartre. Gagasan ini dapat diutarakan ulang - tidak diperlukan pembenaran moral atas suatu tindakan untuk melaksanakan atau melaksanakannya. Hal ini tidak berarti meninggalkan moralitas, namun sebaliknya, menekankan kerasnya kriteria moralitas. Yang tidak bermoral justru adalah pengubahan nama kejahatan menjadi kebaikan, kejahatan menjadi prestasi, yang dilakukan dengan mengacu pada kemanfaatan, perlunya tindakan. Penggantian nama seperti ini dipraktikkan secara luas oleh ideologi politik apologetik, yang mereproduksi formula lama “tujuan menghalalkan segala cara.” Filsuf Rusia Vladimir Solovyov, putra seorang sejarawan terkenal, mengatakan bahwa negara tidak menjanjikan terciptanya surga di bumi, negara hanya berupaya mencegah terciptanya neraka. Kekerasan hukum negara, yang dibawa ke penerapan hukuman mati, bukanlah keadilan tertinggi dan kebaikan surgawi tertinggi, tetapi hanya kejahatan yang dipaksakan sebagai ukuran neraka yang lebih kecil. Inilah saatnya untuk menghargai kata-kata pemikir Rusia dan belajar memperlakukan negara tanpa maksimalisme tradisional Rusia - yaitu, tidak melihat di dalamnya kesucian tertinggi atau kejahatan mutlak.
Dalam situasi kehidupan apa pun, Anda harus membuat pilihan yang tepat dan itu tidak akan sia-sia. Tentang seseorang yang mengikuti jalan kekuatan dalam memerangi kejahatan, Ilyin mengatakan bahwa dia “tidak benar, tapi benar.” Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan yang tidak sepele: kebenaran bukanlah kepolosan dan kepolosan bukanlah kebenaran. Panggilan seseorang yang dipahami secara agama dalam memerangi kejahatan disebut “jalan pedang Ortodoks”. Semua asosiasi dengan Perang Salib atau jihad Ortodoks akan sia-sia. Filsafat tidak peduli dengan membenarkan kejahatan atau mensakralkan kekerasan. Upaya untuk membedakan secara terminologis antara penggunaan kekerasan yang “buruk” dan “baik” terus terjadi. Mengomentari peristiwa Oktober 1993 di ORT, Nikolai Svanidze merumuskan pemikirannya sebagai berikut: kejahatan ditandai dengan agresi, dan kebaikan memiliki kekuatan. Saat menerbitkan pemikirannya tentang konsekuensi serangan teroris 11 September 2001, Vladimir Voinovich memberi judul artikelnya “Kekuatan melawan kekerasan.” Ya, kompleksitas masalahnya terletak pada kenyataan bahwa kekuatan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bertikai; kekuatan tersebut dapat berada di pihak yang baik dan dapat berada di pihak yang jahat. Namun, penggunaan kekuatan fisik apa pun selalu merupakan kekerasan, meskipun dipaksa atau diperlukan.
Lalu, bagaimana beberapa orang yang melakukan tindakan kekerasan berbeda dari orang lain? Teroris, revolusioner, banyak bandit ideologis percaya bahwa mereka mempraktikkan kekerasan suci untuk tujuan yang besar. Seorang pelaku bom bunuh diri, yang melakukan serangan teroris, berharap bisa langsung menuju surga umat Islam. Sebaliknya, orang yang bermoral tidak pernah berpikir bahwa ia berbuat baik ketika ia menggunakan kekerasan dan meyakini bahwa hal itu benar. Di satu sisi, karena kekerasan digunakan untuk kebaikan dan bukan kejahatan, maka kebaikan tidak berhenti menjadi kebaikan. Namun di sisi lain, kekerasan tidak berhenti menjadi kekerasan karena digunakan untuk kebaikan. Bagaimana kekerasan bisa dibenarkan? Tidak ada apa-apa. Namun, filsafat mengajarkan bahwa terkadang melakukan tindakan kekerasan itu perlu dan pantas, meski tidak ada pembenaran untuk itu.
Argumen pertama yang mendukung penggunaan kekerasan dalam melawan kejahatan adalah sederhana dan jelas. Meskipun metode kasih, pengampunan, balas dendam dan nir-kekerasan yang diuraikan dalam Khotbah di Bukit Yesus Kristus lebih sempurna dan lebih disukai, namun tidak semua metode tersebut efektif dan efisien dalam semua kasus. Menyelesaikan masalah tanpa kekerasan selalu lebih baik, namun hal ini tidak selalu memungkinkan. Dalam konflik-konflik di dunia modern, situasi yang dikenal ketika, seperti yang mereka katakan, proses negosiasi menemui jalan buntu.
Argumen lain yang mendukung perlunya menekan kekerasan dengan kekerasan dikaitkan dengan adanya dua sisi dalam setiap kejahatan dan kejahatan – bahaya individu dan sosial. Pengampunan Kristiani atas pelanggaran yang ditimpakan kepada saya, ketidakbersalahan terhadap orang yang menyakiti saya, adalah mungkin, meskipun hal itu berisiko mengulangi kejahatan tersebut. Jika seseorang tidak bersedia menjadi pemerkosa sebagai respons terhadap kekerasan, ia mungkin harus memberikan pipi yang lain untuk menerima pukulan lain. Namun bahkan dalam Injil tidak disebutkan bahwa kita mempunyai hak, apalagi kewajiban moral, untuk memberikan pipi orang lain kepada seorang pemerkosa. Dan ini adalah konsekuensi sosial yang paling mungkin terjadi dari sikap penuh belas kasihan terhadap musuh pribadi kita, yaitu tidak menghentikan tindakannya dengan kekerasan. Dengan tidak menanggapi kekerasan dengan kekerasan, saya melindungi kemurnian moral saya, meskipun saya berisiko menjadi korban lagi. Namun, selain diri Anda sendiri, Anda juga perlu melindungi dan menyelamatkan orang-orang di sekitar Anda. Ini juga merupakan kewajiban moral kita.
Pada tanggal 4 April 1866, Dmitry Karakozov menembak Alexander II, sebagaimana dibuktikan dengan plakat peringatan di kisi-kisi Taman Musim Panas yang terkenal. Upaya tersebut tidak berhasil dan teroris yang ditangkap menulis petisi pengampunan atas nama pejabat tinggi yang ingin dia bunuh. Resolusi tanggapan tsar berbunyi: sebagai seorang Kristen saya memaafkan, tetapi sebagai penguasa saya tidak bisa memaafkan. Apakah solusi ini tidak konsisten? Bisakah kebijakan publik hanya dipandu oleh prinsip Kristiani yaitu mengasihi musuh? Jelaslah bahwa tanggung jawab moral seorang Kristen terhadap hati nuraninya dan Tuhannya serta tanggung jawab sosial seorang warga negara atau politisi terhadap orang lain tidaklah bersamaan. Mereka tidak cocok, tapi juga tidak bertentangan.
Kejahatan juga bermuka dua dalam arti terurai menjadi perasaan jahat, niat kriminal, keadaan mental agresif dan penerapannya dalam tindakan, serta konsekuensinya bagi orang-orang di sekitarnya. Artinya, ia memiliki bentuk internal dan eksternal. Kata-kata Raskolnikov dari novel Dostoevsky bahwa dia tidak membunuh pegadaian tua itu, tetapi menghancurkan jiwanya yang abadi, justru menunjukkan dualisme kejahatan apa pun. Kejahatan yang bermuka dua ini adalah argumen ketiga yang mendukung metode kekerasan dalam memerangi kekerasan. Tentu saja, melawan kerusakan mental, kekuatan fisik apa pun sama sekali tidak ada artinya. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk tidak merasakan kebencian dan kemarahan. Namun, kekerasan dapat mencegah penjahat melaksanakan niat misantropisnya. Seseorang tidak boleh menipu diri sendiri, hanya bentuk kejahatan eksternal yang dapat dikalahkan dengan kekuatan, tetapi ini sudah banyak.
Hipostasis kejahatan internal dan eksternal penting tidak hanya dalam kaitannya dengan penjahat, tetapi juga dalam kaitannya dengan pembalas dendam, pejuang melawan kejahatan, dan aktivis hak asasi manusia. Penggunaan senjata, “jalan pedang”, tentu saja, merupakan jalan masuk ke dalam lingkup kejahatan eksternal. Ungkapan “langkah-langkah yang memadai akan diambil” berarti bahwa metode dan cara mereka sendiri akan digunakan untuk melawan kekerasan. Namun motivasi internal dari tindakan kekerasan harus dimurnikan dari kemarahan, kebencian, kehausan akan balas dendam dan darah. Sehingga Anda bisa berkata, seperti Alexander II, “ini hanya bisnis, hanya bisnis, bukan masalah pribadi.”
Partisipasi terus-menerus dari Vladimir Dobrenkov, dekan Fakultas Sosiologi di Universitas Negeri Moskow, ayah dari seorang putri yang dibunuh secara brutal, dalam berbagai diskusi publik dan acara bincang-bincang tentang masalah penghapusan atau mempertahankan hukuman mati di Rusia menimbulkan kebingungan. Dia bertindak sebagai siapa: seorang ahli yang tidak memihak dalam masalah sosial atau seorang ayah yang berduka dan memiliki dendam pribadi terhadap dunia bawah? Kesedihan orang lain membangkitkan simpati dan rasa hormat, tetapi sangat sulit untuk memisahkan kebenaran dari kesedihan, dan sangat tidak mungkin untuk menyimpulkannya dari kebencian. Inilah yang ditulis oleh filsuf Rusia Semyon Frank tentang hal ini dalam sebuah buku berjudul “The Meaning of Life”: “Semakin sedikit permusuhan pribadi dalam jiwa seorang penentang dan semakin dia secara internal memaafkan musuh-musuh pribadinya, semakin besar pula perjuangannya. , dengan segala keseriusan yang diperlukan, secara rohani atau lebih tepatnya, lebih layak.” Dalam kata-kata Yesus Kristus, “Bukan damai sejahtera yang Kuberikan kepadamu, melainkan pedang,” mereka biasanya melihat semacam kontradiksi terhadap perintah kasih bahkan terhadap musuh dari Khotbah di Bukit. Namun perintah cinta dapat dipahami bukan sebagai hukum yang melarang atau menunjukkan tindakan eksternal tertentu, tetapi hanya sebagai indikasi perlunya mencapai tatanan mental internal yang benar. Dan kemudian belas kasihan internal, pendendam, dan cinta kasih yang baik terhadap umat manusia ternyata sejalan dengan penggunaan kekuatan eksternal yang keras untuk mencegah terjadinya kejahatan.
Sindrom Helsinki atau Stockholm juga bukan merupakan suatu hal yang sangat wajar. Perasaan tragis para sandera dan kerabatnya selalu bisa dimengerti. Namun jelas juga bahwa keputusan-keputusan politik yang penting kadang-kadang harus dibuat bukan berdasarkan perasaan-perasaan ini, melainkan berdasarkan perasaan-perasaan tersebut. Mungkin itu kejam. Namun dalam rasionalitas dan keadilan terdapat unsur kekejaman yang tidak bisa dihindari. Sulit untuk mengatasi kebencian yang bersifat balas dendam. Lebih sulit lagi untuk dibimbing oleh akal, dan bukan hanya oleh rasa kasihan dan simpati. Meskipun hal ini mungkin diperlukan untuk menyelamatkan, tidak hanya diri Anda sendiri, tetapi juga orang lain.
Kesimpulannya sangat serius: peran penyelamat mungkin lebih sulit dan mengerikan daripada peran sandera. Karena dalam aksi antiteroris ada inisiatif intersepsi tertentu. Jika pihak berwenang secara pasif tidak memberikan perlawanan yang kuat, maka calon korban akan disalahkan pada teroris, dan jika tindakan tegas diambil untuk menyelamatkan para sandera, maka calon korban akan disalahkan pada pihak penyelamat. Mereka tidak akan diberi ucapan terima kasih atas mereka yang diselamatkan, namun akan disalahkan atas kematian orang mati. Inilah logika situasinya, yang kami amati dalam penilaian penyerbuan Pusat Teater Dubrovka di Moskow, yang direbut oleh teroris.
Contoh lain dari sifat tragis melawan kejahatan dengan kekerasan adalah keputusan yang diambil oleh Presiden Amerika George W. Bush untuk menembak jatuh pesawat keempat yang ditangkap teroris dengan rudal pada 11 September 2001. Yang dimaksudkan untuk menabrak gedung Capitol di Washington, yang menampung Kongres AS, dan jatuh di negara bagian Pennsylvania karena perlawanan terhadap teroris yang dilakukan oleh para penumpang kapal. Karena keadaan, perintah untuk menembak jatuh pesawat tidak pernah dilaksanakan. Namun, perintah telah diberikan, keputusan telah dibuat. Keputusan ini sulit, namun menyelamatkan nyawa. Ketidakmampuan untuk mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab moral atas keputusan tersebut adalah sebuah bencana.
Kekuatan bukan hanya kemungkinan terjadinya kekerasan, tetapi juga komponen kebaikan dan cinta. Cinta selalu berupa keinginan untuk berbuat baik kepada orang yang kita cintai. Dan cinta yang kuat bukanlah nafsu yang merusak, melainkan kemampuan berbuat baik. “Setiap cinta yang besar,” tulis Nietzsche dalam Such Spoke Zarathustra, “di atas segalanya adalah kasih sayang.” Kata ganti posesif miliknya menunjukkan bahwa cinta sama sekali tidak berdiri di luar belas kasih, tetapi mampu mengatasi rasa kasihan yang terkandung di dalamnya. Cinta bisa menuntut kita untuk mengatasi rasa kasihan, yang membuatnya lebih buruk daripada kematian.
Filsafat Nietzschean berbicara tentang dua jenis cinta - cinta-kekuatan dan cinta-kelemahan. Mereka berbeda dalam peran perempuan sebagai perawat dan fungsi laki-laki sebagai ahli bedah. Dalam kasus pertama, cinta identik dengan rasa kasihan, yang meringankan rasa sakit dan penderitaan, dalam kasus kedua, cinta identik dengan kekuatan, kemampuan kejam untuk menimbulkan rasa sakit. Keduanya adalah cinta, bukan kebencian, hanya diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Cinta wanita yang tersirat dalam kelemahan ternyata adalah kebaikan, dan cinta bedah pria bertujuan bukan untuk menunjukkan kebaikan diri sendiri, tetapi untuk secara aktif mengupayakan kebaikan orang yang ditolong. Kasihan adalah kelumpuhan tindakan seperti amputasi. Menunjukkan rasa kasihan dapat merugikan kesehatan dan kehidupan, namun menunjukkan kekejaman dapat menyelamatkan seseorang. Kebaikan dan kebaikan hanya berhubungan secara gramatikal, dalam kehidupan bisa menjadi bentuk alternatif hubungan antarmanusia.
Dalam novel terkenal The Unbearable Lightness of Being, Milan Kundera berkata tentang pahlawannya: “Kelemahan Franz disebut kebaikan.” Kebaikan adalah satu-satunya perwujudan cinta orang lemah, kebaikan adalah perwujudan cinta orang kuat. Tentu saja kita membutuhkan keduanya. Menariknya, filsuf agama Rusia Semyon Frank mengakui nilai tesis anti-Kristen Nietzsche tentang pentingnya cinta, yang mampu mengatasi rasa kasihan. Hal ini memberinya kesempatan untuk mempertanyakan sifat aksiomatik dari gagasan Dostoevsky bahwa semua kemajuan manusia tidak sebanding dengan air mata seorang anak. Setiap ibu tahu bahwa demi kesejahteraan fisik dan mental anaknya, dia harus siap mengorbankan kesenangannya. Baik pengobatan, pendidikan, maupun keselamatan tidak sepenuhnya menyakitkan, hanya menimbulkan kesenangan. Keengganan untuk menunjukkan kekerasan dan paksaan atau menimbulkan rasa sakit adalah keengganan untuk mencintai.
Pemecahan masalah moral dan politik sering kali melibatkan jawaban atas pertanyaan: Apakah kita mempunyai kekuatan untuk menggunakan kekerasan? Atau akankah kita memiliki kekuatan untuk menanggung kenyataan bahwa dalam situasi ekstrim kita menunjukkan ketidakberdayaan?