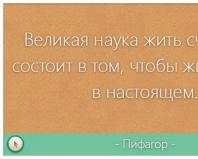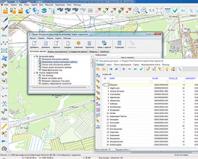Ciri-ciri filsafat Renaisans, humanisme, reformasi. Ciri khas pemikiran filosofis Renaisans. Reformasi. Kontra-Reformasi. Tahapan filsafat Renaisans
Renaisans, menurut beberapa sumber, dimulai pada abad ke-14 - ke-17. menurut yang lain - pada abad XV - XVIII. Istilah Renaisans (Renaissance) diperkenalkan untuk menunjukkan bahwa di era ini nilai-nilai terbaik dan cita-cita zaman kuno dihidupkan kembali - arsitektur, patung, lukisan, filsafat, sastra. Namun istilah ini ditafsirkan secara kondisional, karena tidak mungkin mengembalikan seluruh masa lalu. Ini bukanlah kebangkitan masa lalu dalam bentuknya yang murni - ini adalah penciptaan yang baru dengan menggunakan banyak nilai spiritual dan material dari zaman kuno.
Periode terakhir Renaisans adalah era Reformasi, yang mengakhiri revolusi progresif terbesar dalam perkembangan kebudayaan Eropa.
Dimulai di Jerman, Reformasi melanda sejumlah negara Eropa dan menyebabkan kemurtadan dari Gereja Katolik di Inggris, Skotlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, Belanda, Finlandia, Swiss, Republik Ceko, Hongaria, dan sebagian Jerman. Ini adalah gerakan keagamaan dan sosial politik yang luas yang dimulai pada awal abad ke-16 di Jerman dan bertujuan untuk mereformasi agama Kristen.
Kehidupan spiritual pada masa itu ditentukan oleh agama. Namun gereja tidak mampu menolak tantangan zaman. Gereja Katolik mempunyai kekuasaan atas Eropa Barat dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, namun mendapati dirinya berada dalam situasi yang menyedihkan. Muncul sebagai gerakan kaum yang terhina dan diperbudak, kaum miskin dan teraniaya, agama Kristen menjadi dominan pada Abad Pertengahan. Dominasi Gereja Katolik yang tidak terbagi-bagi dalam segala bidang kehidupan pada akhirnya menyebabkan kemerosotan dan pembusukan internalnya. Kecaman, intrik, pembakaran di tiang pancang, dll. dilakukan atas nama guru cinta dan belas kasihan - Kristus! Dengan mengkhotbahkan kerendahan hati dan pantangan, gereja menjadi sangat kaya. Dia mendapat untung dari segalanya. Jajaran tertinggi Gereja Katolik hidup dalam kemewahan yang belum pernah terdengar sebelumnya, terlibat dalam hiruk pikuk kehidupan sosial yang bising, sangat jauh dari cita-cita Kristiani.
Jerman menjadi tempat lahirnya Reformasi. Permulaannya dianggap sebagai peristiwa tahun 1517, ketika doktor teologi Martin Luther (1483 - 1546) menyampaikan 95 tesisnya menentang penjualan surat pengampunan dosa. Sejak saat itu, pertarungan panjangnya dengan Gereja Katolik dimulai. Reformasi dengan cepat menyebar ke Swiss, Belanda, Perancis, Inggris, dan Italia. Di Jerman, Reformasi dibarengi dengan Perang Tani, yang berlangsung dalam skala sedemikian rupa sehingga tidak ada gerakan sosial di Abad Pertengahan yang dapat menandinginya. Reformasi menemukan ahli teori barunya di Swiss, tempat pusat reformasi terbesar kedua setelah Jerman. Di sana pemikiran Reformasi akhirnya diformalkan oleh John Calvin (1509 – 1564) yang dijuluki “Paus Jenewa.” Pada akhirnya Reformasi melahirkan arah baru dalam agama Kristen yang menjadi landasan spiritual peradaban Barat – Protestantisme. .Protestanisme membebaskan masyarakat dari tekanan agama dalam kehidupan praktis. Agama menjadi urusan pribadi seseorang. Kesadaran beragama digantikan oleh pandangan dunia sekuler. Ritual keagamaan disederhanakan. Namun pencapaian utama Reformasi adalah peran khusus yang diberikan kepada individu. dalam komunikasi individualnya dengan Tuhan. Karena kehilangan mediasi gereja, manusia kini harus bertanggung jawab atas tindakannya, yakni tanggung jawab yang jauh lebih besar diberikan kepadanya. Berbagai sejarawan memecahkan masalah hubungan antara Renaisans dan Reformasi dalam Baik Reformasi maupun Renaisans menempatkan kepribadian manusia sebagai pusatnya, energik, berjuang untuk mentransformasi dunia, dengan prinsip kemauan yang kuat. Namun Reformasi pada saat yang sama mempunyai dampak yang lebih bersifat disipliner: ia mendorong individualisme, tetapi menempatkannya dalam kerangka moralitas yang ketat berdasarkan nilai-nilai agama.
Renaisans berkontribusi pada munculnya pribadi yang mandiri dengan kebebasan memilih moral, mandiri dan bertanggung jawab dalam penilaian dan tindakannya. Para pengusung gagasan Protestan mengungkapkan tipe kepribadian baru dengan budaya dan sikap baru terhadap dunia.
Reformasi menyederhanakan, merendahkan dan mendemokratisasi gereja, menempatkan iman pribadi di atas manifestasi religiusitas yang lahiriah, dan memberikan persetujuan ilahi terhadap norma-norma moralitas borjuis.
Gereja berangsur-angsur kehilangan posisinya sebagai “negara di dalam negara”; pengaruhnya terhadap kebijakan dalam dan luar negeri menurun secara signifikan, dan kemudian hilang sama sekali.
Ajaran Jan Hus mempengaruhi Martin Luther yang secara umum bukanlah seorang filsuf atau pemikir. Namun ia menjadi seorang reformis Jerman, terlebih lagi pendiri Protestantisme Jerman.
kebangkitan filsafat humanisme global
Pemahaman tentang agama Kristen sebagai sistem moralitas yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata bertentangan tidak hanya dengan pandangan abad pertengahan tentang tidak pentingnya sifat manusia, tetapi juga dengan gagasan tentang keberdosaan manusia, yang dipertahankan oleh Reformasi. . Oleh karena itu, “humanisme Kristen” Erasmus dari Rotterdam menimbulkan kecaman tidak hanya dari para penjaga asketisme abad pertengahan yang lama, penjaga kemurnian dogmatis Katolik tradisional, tetapi juga lebih banyak lagi dari para pengikut Luther dan Calvin.
Pertanyaan tentang hakikat manusia pada dasarnya merupakan pusat polemik antara Erasmus dan Luther mengenai pertanyaan teologis tentang kehendak bebas dan predestinasi ilahi. Dalam bentuk teologis, pertanyaan tentang kebebasan dan kebutuhan, determinisme perilaku manusia dan tanggung jawab manusia dimunculkan di sini. Jika Erasmus berangkat dari gagasan humanistik tentang manusia sebagai “makhluk hidup yang mulia, yang demi Tuhan sajalah mekanisme dunia yang menyenangkan ini dibangun,” seperti yang ia tulis pada tahun 1501 dalam risalah “Manual of the Christian Warrior,” maka premis awal Luther adalah bahwa umat manusia ditakdirkan menuju kehancuran karena dosa asal, manusia sendiri tidak dapat diselamatkan dengan usahanya sendiri, dengan dirinya sendiri ia tidak dapat berpaling pada kebaikan, melainkan cenderung hanya pada kejahatan. Erasmus, yang mengakui, sesuai dengan ajaran Kristen, bahwa sumber dan hasil keselamatan kekal bergantung pada Tuhan, namun percaya bahwa jalannya kehidupan manusia di dunia bergantung pada manusia dan pada pilihan bebasnya dalam kondisi tertentu, yang merupakan sebuah prasyarat untuk tanggung jawab moral. Penting bagi Luther untuk membatasi permasalahannya hanya pada keselamatan setelah kematian, sementara Erasmus mengajukan pertanyaan yang lebih luas mengenai moralitas manusia secara umum. Doktrin Lutheran (dan bahkan Calvinis yang lebih kaku) tentang predestinasi ilahi yang mutlak, yang menurutnya seseorang hanya melalui rahmat ilahi dapat ditentukan sejak semula untuk keselamatan abadi, terlepas dari kehendak, perbuatan, dan tindakannya sendiri, tentang ketidakmungkinan seseorang mencapai keselamatannya sendiri, menjadi alasan utama perbedaan antara humanis Erasmia dan gerakan reformasi. Dalam polemik dengan para reformis, kaum humanis membela doktrin kebebasan dan martabat manusia. Mereka membandingkan fanatisme agama dengan gagasan pemahaman yang “luas” tentang agama Kristen, yang memungkinkan keselamatan semua orang yang hidup berbudi luhur, terlepas dari perbedaan agama. Hal ini, serta sikap bebas terhadap tradisi alkitabiah, polemik terhadap beberapa dogma terpenting Kekristenan, menyebabkan konflik mendalam antara kaum humanis dan gereja-gereja baru dari Reformasi yang menang, yang dalam banyak hal ternyata memusuhi humanistik. cita-cita.
Dampak humanisme Kristen Erasmus dari Rotterdam terhadap kebudayaan Eropa pada abad ke-16. sangat luar biasa: orang-orang dan pengikutnya yang berpikiran sama dapat ditemukan di seluruh Eropa Katolik dan Protestan dari Inggris hingga Italia, dari Spanyol hingga Polandia.
Tujuannya adalah reformasi Katolik, demokratisasi Gereja, dan pembentukan hubungan antara Gereja, Tuhan dan umat beriman. Prasyarat munculnya arah ini adalah:
- · krisis feodalisme;
- · memperkuat kelas borjuasi komersial dan industri;
- · melemahnya fragmentasi feodal, pembentukan negara-negara Eropa;
- · ketidaktertarikan para pemimpin negara-negara tersebut dan elit politik terhadap kekuasaan Paus dan Gereja Katolik yang bersifat supranasional dan bersifat supranasional;
- · krisis, kemerosotan moral Gereja Katolik, keterisolasiannya dari masyarakat, ketertinggalan dalam kehidupan;
- · penyebaran ide-ide humanisme di Eropa;
- · pertumbuhan kesadaran diri pribadi, individualisme;
- · Tumbuhnya pengaruh ajaran agama dan filsafat yang anti-Katolik, ajaran sesat, mistisisme, dan Husisme.
Ada dua gerakan utama dalam Reformasi: burgher-evangelis (Luther, Zwingli, Calvin) Dan rakyat (Münzer, Anabaptis, Penggali dll.).
Martin Luther menganjurkan komunikasi langsung antara Tuhan dan orang percaya, percaya bahwa tidak boleh ada Gereja antara Tuhan dan orang percaya. Gereja sendiri, menurut para reformis, harus menjadi demokratis, ritual-ritualnya harus disederhanakan dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Dia percaya bahwa perlu untuk mengurangi pengaruh Paus dan pendeta Katolik terhadap kebijakan negara. Pekerjaan melayani Tuhan bukan hanya sebuah profesi yang dimonopoli oleh para ulama, tetapi juga merupakan fungsi dari seluruh kehidupan umat Kristiani. Pemikir percaya bahwa indulgensi perlu dilarang. Ia percaya bahwa otoritas lembaga negara harus dipulihkan, kebudayaan dan pendidikan harus dibebaskan dari dominasi dogma Katolik.
John Calvin(1509 - 1564) percaya bahwa gagasan utama Protestantisme adalah gagasan predestinasi: manusia pada awalnya ditentukan oleh Tuhan untuk diselamatkan atau binasa. Semua orang harus berharap bahwa merekalah yang ditakdirkan untuk diselamatkan. Para pembaharu percaya bahwa mengungkapkan makna hidup manusia di bumi adalah sebuah profesi yang tidak hanya sebagai sarana mencari uang, tetapi juga tempat mengabdi kepada Tuhan. Sikap teliti dalam bekerja adalah jalan menuju keselamatan, keberhasilan dalam bekerja adalah tanda keterpilihan Tuhan. Di luar pekerjaan, seseorang harus rendah hati dan pertapa. Calvin mempraktikkan gagasan Protestantisme dengan memimpin gerakan reformasi di Jenewa. Dia mendapatkan pengakuan atas Gereja yang direformasi sebagai Gereja resmi, menghapuskan Gereja Katolik dan kekuasaan Paus, dan melakukan reformasi baik di dalam Gereja maupun di kota. Terima kasih Calvin. Reformasi menjadi fenomena internasional.
Thomas Munzer(1490 - 1525) memimpin arah Reformasi yang populer. Dia percaya bahwa reformasi tidak hanya diperlukan bagi Gereja, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari perubahan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan universal, “kerajaan Allah” di Bumi. Penyebab utama segala kejahatan, menurut pemikir, adalah kesenjangan, pembagian kelas (kepemilikan pribadi dan kepentingan pribadi), yang harus dihancurkan; semuanya harus menjadi milik bersama. Tuhan menghendaki agar kehidupan dan aktivitas manusia sepenuhnya tunduk pada kepentingan masyarakat. Kekuasaan dan properti, menurut sang reformator, harus menjadi milik rakyat jelata - “pengrajin dan pembajak”. Pada tahun 1524 - 1525 Münzer memimpin Perang Tani yang anti-Katolik dan revolusioner dan meninggal.
Erasmus dari Rotterdam(1469-1536) - Di antara karya-karyanya, “Praise of Stupidity” yang terkenal menonjol, di mana Erasmus dalam bentuk sarkastik memberikan pujian kepada Lady Stupidity, yang berkuasa atas dunia dan yang dipuja semua orang. Di sini dia membiarkan dirinya mengejek para petani yang buta huruf dan para teolog kelas atas - pendeta, kardinal, dan bahkan paus.
Patut diperhatikan apa yang disebut “Enchiridion, atau Senjata Pejuang Kristen” dan “Cacian, atau Wacana tentang Kehendak Bebas.” Karya pertama dikhususkan untuk filsafat Kristus.
Erasmus sendiri menganggap dirinya seorang Kristen sejati dan membela cita-cita Gereja Katolik, meskipun tentu saja ia tidak menyukai banyak hal - kelemahan moral, pelanggaran hukum, penyalahgunaan berbagai macam dogma Katolik, khususnya dogma indulgensi, dll. . Namun, Erasmus tidak berbagi banyak ketentuan yang dianggap remeh pada Abad Pertengahan. Oleh karena itu, ia adalah seorang pendidik dalam semangat, percaya bahwa semua orang diciptakan oleh Tuhan sama dan identik, dan keluhuran mereka tidak bergantung pada kepemilikan mereka sejak lahir dalam keluarga bangsawan atau kerajaan, tetapi pada pendidikan, moralitas, dan pendidikan mereka.
Filsafat harus bermoral; hanya filsafat seperti itu yang dapat disebut filsafat Kristus yang sejati. Filsafat harus menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia, permasalahan manusia, tetapi filsafat skolastik tidak memperhatikan hal ini. Filsafat harus hadir dalam seluruh kehidupan seseorang, menuntunnya menjalani kehidupan - karya utama Erasmus, “Weapons of the Christian Warrior” (1501), dikhususkan untuk topik inilah.
Arti Filosofi Reformasi dalam hal ini berfungsi sebagai pembenaran ideologis atas perjuangan politik dan bersenjata untuk reformasi Gereja dan melawan Katolik, yang berlanjut sepanjang abad ke-16. dan selanjutnya di hampir semua negara Eropa. Akibat dari perjuangan ini adalah jatuhnya agama Katolik di sejumlah negara dan perpecahan agama di Eropa: kejayaan berbagai aliran Protestan (Lutheranisme, Calvinisme, dll) di Eropa Utara dan Tengah - Jerman, Swiss, Inggris Raya, Belanda , Denmark, Swedia, Norwegia; pelestarian agama Katolik di negara-negara Eropa Selatan dan Timur - Spanyol, Prancis, Italia, Kroasia, Polandia, Republik Ceko, dll.
Dalam jurnalisme klerikal zaman Renaisans kita tidak akan menemukan semangat untuk kelahiran kembali (pengangkatan dan pemulihan spiritual). Perwakilannya yang jujur dan penuh perhatian dipenuhi dengan kecemasan yang mendalam; mereka berbicara tentang kerusakan kelas suci, kemerosotan moral yang meluas, keadaan gereja dan iman yang membawa bencana. Dari kegelisahan ini, yang bergema di kalangan luas kaum awam, lahirlah gerakan yang penuh semangat dan kreatif untuk pembaruan iman, yang berbalik melawan kepausan dan pada sepertiga pertama abad ke-16 memperoleh cakupan yang benar-benar demokratis. Gerakan ini merupakan reformasi agama. Ini dimulai dengan khotbah Luther yang energik dan berlanjut melalui peristiwa-peristiwa dramatis seperti pembentukan Gereja Lutheran di kerajaan-kerajaan Jerman, kebangkitan Anabaptisme dan Perang Tani tahun 1524-1525; berdirinya Calvinisme di Swiss; penyebaran Protestantisme di Belanda, Skandinavia, Inggris dan Perancis; perjuangan kemerdekaan Belanda (1568-1572); perang agama yang mengerikan pada paruh pertama abad ke-17, yang berujung pada terbentuknya gagasan toleransi beragama dan pemisahan gereja dan negara; munculnya “generasi kedua” denominasi Protestan (Socinian, Pietists, Herrnhuters, Quaker, Mormon, dll.); Revolusi Inggris 1645-1648 Pemimpin Reformasi yang diakui adalah Martin Luther (1483-1546), Ulrich Zwingli (1484-1531) dan John Calvin (1509-1564).
Tidak ada keraguan bahwa Reformasi awal mewarisi inisiatif utama Renaisans – semangat personalistiknya. Reformasi mewarisi inisiatif utama Renaisans - semangat personalistiknya. Melanjutkan upaya utama - personalistik - para humanis abad 14-15, para reformis pertama melakukan upaya “untuk menciptakan ajaran baru tentang Tuhan, dunia dan manusia […] berdasarkan bukti kognitif gratis.” Kaum humanis Renaisans dan perwakilan pemikiran Reformasi awal dipersatukan oleh kesedihan hati nurani yang bebas, gagasan untuk kembali ke asal usul (dalam satu kasus - ke kuno dan evangelis, di sisi lain - ke evangelis dan patristik ); keinginan untuk melakukan penafsiran moral terhadap Kitab Suci; permusuhan yang mendalam terhadap skolastisisme, dogma, dan rumusan tradisi gereja yang membeku. Kebetulan-kebetulan ini begitu jelas sehingga lebih dari satu kali menimbulkan godaan untuk menggabungkan Renaisans dan Reformasi menjadi satu era sosiokultural dan spiritual. Namun sisi lain dari permasalahan ini tidak kalah pentingnya. Reformasi bukan hanya kelanjutan dari Renaisans, tetapi juga sebuah protes terhadapnya - sebuah protes yang tegas dan penuh semangat, terkadang dituangkan ke dalam formula-formula fanatik anti-humanisme dan bahkan misantropi. Menganut formula-formula ini berarti mengabaikan cara berpikir yang beradab dan manusiawi. Dan pada saat yang sama, kita tidak bisa tidak melihat bahwa ketidaksepakatan antara Reformasi dan Renaisans cukup beralasan dan bahwa cara berpikir beradab itu sendiri banyak disebabkan oleh ketidaksepakatan ini. Bersolidaritas dengan pengakuan Renaisans atas Diri individu manusia, para reformis awal dengan tegas menolak, namun, pengagungan generik Renaisans terhadap manusia, peninggiannya sebagai sebuah kategori, sebagai jenis makhluk khusus (atau - dalam bahasa teologis - sebagai makhluk khusus). jenis makhluk). Dalam pujian Renaisans atas kesempurnaan manusia (terutama yang ekspresif, misalnya oleh Marsilio Ficino), orang dapat mendengar kecenderungan untuk mendewakan manusia.
Renaisans (Renaisans)- era dalam sejarah kebudayaan dan filsafat, yang ditandai dengan pulihnya minat terhadap budaya dan filsafat kuno. Pada Abad Pertengahan, zaman kuno umumnya dinilai negatif, meskipun ada beberapa gagasan filosofis yang dipinjam. L. Valla menyebut Abad Pertengahan sebagai “zaman kegelapan”, yaitu. masa fanatisme agama, dogmatisme, dan obskurantisme. Renaisans secara geografis dan kronologis terbagi menjadi selatan (terutama Italia abad 14-16) dan utara (Prancis, Jerman, Belanda, abad 15-16).
Ciri-ciri filsafat Renaisans:
- antroposentrisme– gagasan tentang “martabat” (tempat) khusus seseorang di dunia;
- humanisme– dalam arti luas: suatu sistem pandangan yang mengakui nilai seseorang sebagai individu, haknya atas kebebasan, kebahagiaan, pengembangan dan realisasi kemampuan kreatif;
- sekularisasi– budaya dan filsafat memperoleh karakter sekuler, terbebas dari pengaruh teologi, namun proses ini tidak sampai pada munculnya ateisme;
- rasionalisme– kepercayaan terhadap kekuatan nalar sebagai sarana pengetahuan dan “pembuat undang-undang” tindakan manusia meningkat;
- orientasi anti-skolastik– Anda perlu mempelajari bukan kata-kata, tetapi fenomena alam;
- panteisme– doktrin filosofis yang mengidentifikasi Tuhan dan dunia;
- interaksi dengan sains;
- interaksi dengan budaya seni.
Humanisme sebagai gerakan budaya Renaisans, terutama di Italia, Florence terbagi menjadi humanisme “awal” (“sipil”), 14 – babak pertama. abad ke 15 (C. Salutati, L. Valla, L.B. Alberti, D. Manetti, P. della Mirandola) dan "terlambat", lantai 2 abad ke-15 – ke-16 (Neoplatonisme oleh M. Ficino, neo-Aristotelianisme oleh P. Pomponazzi). Sejak akhir abad ke-15. Gerakan humanistik berpindah ke Belanda (E. Rotterdam), Jerman (I. Reuchlin), Perancis (M. Montaigne), Inggris (T. More). Humanisme terbagi menjadi “sekuler”, yang menjauhkan diri dari agama, dan “Kristen” (E. Rotterdam); etikanya memadukan pemahaman humanistik tentang manusia dengan cita-cita Kekristenan awal. Filsuf alam Renaisans: N.Cusansky, N.Copernicus, D.Bruno, G.Galileo. Pemikir sosial: N. Machiavelli, T. Campanella, T. Lebih lanjut.
Kosmologi dan ontologi:
- heliosentrisme – doktrin bahwa bukan Bumi, melainkan Matahari yang menjadi pusat dunia;
- panteisme;
- gagasan tentang kesatuan alam semesta dan hukum-hukumnya;
- gagasan tentang ketidakterbatasan alam semesta Dan banyaknya dunia.
Epistemologi:
- memperkuat posisi akal, mengembangkan metode ilmiah untuk mengetahui alam;
- keraguan– dalam filsafat M. Montaigne: pemeriksaan kritis berdasarkan akal, keraguan mengenai gagasan apa pun, tidak peduli seberapa benar gagasan itu;
- percobaan– oleh G. Galileo: metode utama kognisi hukum alam;
- matematika memainkan peran khusus dalam pengetahuan tentang alam (N. Kuzansky, G. Galileo).
Antropologi filosofis:
- prinsip humanisme;
- rehabilitasi prinsip fisik dalam diri seseorang;
- kesamaan antara mikrokosmos dan makrokosmos– sebuah prinsip yang menunjukkan status khusus manusia di dunia, kemampuannya untuk mengenal Tuhan dan dunia yang diciptakannya (N. Kuzansky, Mirandola);
- kultus kepribadian yang kreatif dan berkembang secara komprehensif.
Etika:
- sekularisasi moralitas– membebaskannya dari sanksi agama;
- humanisme sipil– doktrin yang menyatakan bahwa partisipasi dalam urusan publik dan kenegaraan adalah kewajiban setiap warga negara;
- kebajikan sipil, memastikan subordinasi yang wajar antara kepentingan pribadi di atas kepentingan umum demi kepentingan kebaikan bersama;
- bekerja– faktor utama dalam pembangunan manusia, cara mewujudkan kemampuan kreatif;
- hedonisme– memperoleh kesenangan sebagai tujuan utama hidup manusia;
- kaum bangsawan– sebuah konsep yang mencirikan martabat seseorang bukan berdasarkan asal usulnya, tetapi berdasarkan kualitas dan kelebihan pribadinya;
- gagasan keberuntungan- Keberuntungan hanya datang kepada orang yang aktif dan pekerja keras.
Filsafat sosial:
- Machiavellianisme– sebuah konsep yang mencirikan doktrin sosio-politik N. Machiavelli, yang dituangkan dalam risalah “The Prince”, bahwa politik dan moralitas tidak sejalan dan segala cara dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik;
- utopia– dalam arti luas: sebuah proyek masyarakat ideal yang tidak dapat direalisasikan; dalam arti sempit: nama karya T. More, di mana proyek semacam itu diusulkan, bersama dengan karya “City of the Sun” oleh T. Campanella.
Filsafat sejarah:
- gagasan tentang hukum perkembangan sejarah, yang berkembang selama aktivitas sejarah kolektif manusia, tidak adanya partisipasi Tuhan dalam proses sejarah;
- teori siklus sejarah– doktrin yang menyatakan bahwa semua bangsa melalui tahap-tahap perkembangan yang kurang lebih sama dan berulang;
- konsep peran kepribadian yang luar biasa dalam sejarah sehubungan dengan ide tersebut Harta benda.
Reformasi – V dalam arti luas: gerakan sosio-politik, agama dan ideologi di negara-negara Eropa Tengah dan Barat, yang ditujukan terhadap Gereja Katolik sebagai kekuatan politik dan spiritual, melawan “sekularisasi”, penyalahgunaan pendeta Katolik; V dalam arti sempit: revisi terhadap prinsip dasar agama Katolik, yang menyebabkan munculnya cabang baru agama Kristen - Protestantisme. Reformasi dibagi menjadi burgher-borjuis, dibuktikan dengan ajaran M. Luther (Jerman), W. Zwingli (Swiss), J. Calvin (Prancis - Swiss), dan rakyat, dibuktikan oleh T. Münzer (Jerman).
Ideolog Reformasi Mereka menentang “kerusakan terhadap gereja”, untuk kembali ke “Kekristenan sejati pada zaman para rasul”, “membersihkan” iman dari lapisan sejarah. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan verifikasi Tradisi Suci dengan otoritas Kitab Suci (Alkitab), membandingkan otoritas Alkitab dengan Gereja Katolik, melestarikan sakramen, dogma dan ritual yang berdasarkan pada Alkitab. . Protestantisme mengakui dua dari tujuh sakramen gereja, menghapuskan ibadah orang-orang kudus, puasa wajib dan sebagian besar hari libur gereja. Prinsip:
- "pembenaran karena iman"- prinsip ajaran M. Luther: iman yang tulus adalah satu-satunya syarat keselamatan jiwa, dan "perbuatan baik"- hanya manifestasi iman, dan bukan jalan menuju keselamatan yang mandiri;
- "imam universal"- prinsip ajaran M. Luther: keselamatan tidak memerlukan pendeta dan gereja, setiap orang awam adalah imamnya sendiri, dan kehidupan duniawi adalah pelayanan imam;
- “kebebasan berkeyakinan” (hati nurani)- prinsip ajaran M. Luther: orang percaya memiliki kebebasan internal, hak untuk menafsirkan Alkitab secara mandiri, dan bukan hanya Paus;
- takdir- prinsip ajaran M. Luther: manusia tidak memiliki keinginan bebas, kehendak Tuhan menentukan kehidupan setiap orang;
- "predestinasi mutlak"- prinsip ajaran J. Calvin: Tuhan, bahkan sebelum penciptaan dunia, telah menentukan takdir sebagian orang untuk keselamatan, dan sebagian lainnya untuk kehancuran, dan tidak ada upaya manusia yang dapat mengubahnya, tetapi setiap orang harus yakin bahwa dia adalah “milik Tuhan yang terpilih";
- aktivitas profesional– dalam ajaran J. Calvin: kesuksesan di dalamnya adalah tanda pilihan Tuhan, profesi adalah panggilan, tempat mengabdi kepada Tuhan, kesuksesan profesional itu sendiri berharga, dan bukan merupakan sarana untuk mencapai harta duniawi;
- asketisme duniawi– prinsip ajaran J. Calvin: seseorang dalam kehidupan sehari-hari harus puas hanya dengan apa yang diperlukan untuk hidup.